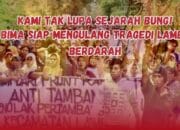Oleh : Ahmad Usman*
Dosen Universitas Mbojo Bima (Alumni UNM dan UNHAS Makassar). Foto: Ist
Menjadikan Kota Bima “BISA”, bukan sebatas gerakan apalagi program “an sich”. Harapan kita adalah lahirnya “budaya” Bersih, Indah, Sehat dan Asri (BISA). Untuk menggapai obsesi mulia seperti itu tidak semudah membalikan telapak tangan atau simsalabim. Butuh perjuangan dan perlu ada itikad baik untuk merubah perilaku kita, yang selama ini abai dan tidak mengindahkan kehidupan bersama yang bersih, indah, sehat dan asri.
Merubah Perilaku, Tidak Serta Merta !
Terdapat beberapa rangsangan dapat menyebabkan orang merubah perilakunya. Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI(2011), beberapa rangsangan, dapat berupa : rangsangan fisik; rangsangan yang bersumber pada keadaan seseorang pada suatu saat; rangsangan rasional; rangsangan bersumber pada pengetahuan dan melihat bukti-bukti nyata; rangsangan emosional; rangsangan karena rasa takut, cinta, harapan-harapan; rangsangan bersumber pada keterampilan seseorang untuk mengadopsi dan melanjutkan perilaku yang baru; jaringan perorangan dan keluarga; rangsangan bersumber dari pengaruh keluarga dan teman; struktur sosial; dan rangsangan bersumber dari dampak faktor sosial, ekonomi, hukum dan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari seseorang.
Manusia bisa berubah dan menerima paradigma atau budaya baru, tidak serta merta. Tapi perlu tahapan. Tahapan itu adalah “know”, “believe”, “attitude”, “behavior”, “habit” dan ”culture” (Samani dan Hariyanto, 2017).
Pertama, tahapan know. Semua stimuli dari akibat interaksi kita dan lingkungan, akan menjadi bahan dasar untuk mengetahui sesuatu, dan selanjutnya berfungsi untuk memicu munculnya perilaku. Pengetahuan (knowledge) adalah hasil tahu dari manusia, yang sekadar menjawab pernyataan ‘what’, misalnya apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2012).
Ranah kognitif dalam Taksonomi Bloom (Pangemanan, 2023) terdiri dari enam level. Pertama, pengetahuan (knowledge). Kemampuan merestitusi atau mengulang kembali informasi. Kedua, pemahaman atau persepsi (comprehension). Kemampuan memahami petunjuk atau permasalahan, menginterpretasikan, dan menyampaikannya kembali dengan kata-kata sendiri. Ketiga, penerapan (application). Kemampuan menerapkan konsep dalam situasi atau praktik yang belum dikenal sebelumnya. Keempat, penguraian atau penjabaran (analysis). Kemampuan menganalisis konsep menjadi beberapa komponen untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif tentang dampak komponen-komponen tersebut terhadap keseluruhan konsep. Kelima, pemaduan (synthesis). Kemampuan menyusun kembali atau menggabungkan komponen-komponen untuk menciptakan makna, pemahaman, atau struktur baru. Keenam, penilaian (evaluation). Kemampuan menilai dan mengevaluasi sesuatu berdasarkan norma, referensi, atau kriteria yang ditentukan
Setiap tingkatan ini memberikan panduan bagi seseorang untuk memahami dan menggunakan pengetahuan secara lebih mendalam, sehingga mereka tak hanya menghafal tetapi juga memahami, menerapkan, bahkan mengevaluasi informasi yang dipelajari. Pertama, mengingat (remembering). Mengingat kembali informasi atau konsep dasar yang sudah dipelajari. Misalnya : menyebutkan kepanjangan dari akronim “BISA”. Kedua, memahami (understanding). Menjelaskan atau menggambarkan konsep dengan kata-kata sendiri. Misalnya : menjelaskan proses perubahan perilaku : Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (“BISA”). Ketiga, menerapkan (applying). Menggunakan informasi atau konsep dalam situasi yang baru atau berbeda. Misalnya : menggunakan perilaku Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (“BISA”) yang telah dipelajari untuk memecahkan soal. Keempat, menganalisis (analyzing). Memecah konsep menjadi bagian-bagian untuk memahami strukturnya. Misalnya : menganalisis perilaku : Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (“BISA”) dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mengevaluasi (evaluating). Membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Misalnya : mengevaluasi perilaku Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (“BISA”) dalam sebuah penelitian. Keenam, mencipta (creating): menggabungkan elemen-elemen untuk menciptakan sesuatu yang baru atau orisinal. Misal : berperilaku bersih, indah, sehat, dan asri baru berdasarkan konsep perilaku “BISA” yang sudah dipelajari.
Kedua, tahapan believe. Setelah kita mengetahui sesuatu yang baru, yang sudah disaring oleh keyakinan kita. Keyakinan yang bersumber dari nilai-nilai yang terbentuk di lingkungan. Jika hal itu bermakna, maka kita pasti menerimanya.
Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal. Keyakinan itu didasarkan atas pengetahuan, opini dan keyakinan yang mungkin dipengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh rasa emosional (Assauri, 2009).Keyakinan atau sebuah kepercayaan adalah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan yang berlangsung dalam jangka panjang. Kepercayaan muncul ketika ada salah satu pihak yakin dengan adanya hubungan kerjasama yang bisa diandalkan serta adanya integritas (Akbar dan Parvez, 2009).
Setelah keyakinan, maka akan timbul sikap yang telah dipengaruhi oleh keyakinan sebelumnya. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang gambaran sesuatu.
Tahapan ketiga yaitu attitude (sikap). Sinergi antara apa yang kita ketahui (know) dengan apa yang kita yakini (belief), akan membuahkan sikap. Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, suka-tidak suka, dan sebagainya (Nototmodjo, 2012).
Sikap merupakan suatu ekpressi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek (Damiati, dkk., 2017). Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecendrungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan (Kotler, 2007).
Indikator sikap positif : seseorang melakukan sesuatu hal yang baik dengan senang hati; seseorang menyukai hal-hal yang baik; seseorang selalu melaksanakan norma-norma yang berlaku; seseorang menyetujui hal-hal yang baik; seseorang suka berpartisipasi dalam kebaikan; seseorang gemar melakukan kebaikan; seseorang menghormati aturan yang berlaku; seseorang patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku; melaksanakan tugas dengan tanggung jawab; dan seseorang selalu memenuhi kewajibannya (Octaviana dan Adinda Juwita Sari, 2024).
Tahapan keempat yakni behavior. Perilaku yang ditampilkan oleh seseorang adalah akumulasi dari know, believe dan attitude. Ketiga paduan tersebut, acapkali disebut sebagai “software”, sedangkan behavior adalah ‘hardware”nya.
Perilaku adalah suatu respon seseorang yang dikarenakan adanya stimulus atau rangsangan dari luar (Notoatmodjo, 2014). Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika. Banyak definisi perilaku berkembang sejalan dengan penelitian mengenai perilaku manusia. Sebagian orang berpendapat bahwa perilaku itu adalah sinonim dari aktivitas, aksi, kinerja, respons, atau reaksi. Dengan kata lain, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia.
Beberapa faktor penyebab sebuah tindakan atau perilaku, salah satu di antaranya adalah faktor predisposing, merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor predisposing meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat (Green dalam Notoatmodjo, 2014).
Proses terbentuknya perilaku bukan hanya karena adanya lingkungan sekitar, melainkan karena orang lain yang mempengaruhi seorang individu dengan memberikan aturan yang tidak diketahui sebelumnya sehingga akan merubah pola pikir seseorang individu akan suatu hal yang membentuk pola pikir perilakunya (Lestari, 2016).
Tahapan kelima adalah habit. Perilaku yang didemonstrasikan secara konsisten adalah kebiasaan (habit), merupakan bentuk kristalisasi perilaku.
Menarik pendapat Brian Tracy (2005), mengenai hukum kebiasaan bahwa pikiran atau tindakan apa saja yang Anda lakukan secara berulang-ulang, pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan menurut Chaplin (Achyanadia, 2013) adalah reaksi yang diperoleh atau dipelajari, kegiatan yang mempelajari relatif otomatis setelah melewati praktek yang panjang, pola pikir atau sikap yang relatif terus-menerus, karakteristik dan tingkah laku individu, dorongan yang diperoleh atau dipelajari.
Tahapan terakhir atau keenam yakni cultutre. Budaya adalah cerminan dari nilai-nilai yang diketahui dan diyakini. Budaya merupakan pemantapan dari kebiasaan (habit). Pada tahapan inilah, perilaku seseorang sudah melekat dan sulit untuk diubah kembali atau telah terinternalisasi, kendati ada nilai-nilai yang baru.
Beberapa fungsi budaya bagi kehidupan masyarakat. Pertama, sebagai sistem komunikasi. Budaya membantu masyarakat dalam berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol yang dikenal bersama. Kedua, pengontrol sosial. Budaya membantu masyarakat dalam mengontrol perilaku individu agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ketiga, sumber pengetahuan. Budaya menyimpan segala pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya, termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam, memelihara ternak, menyusun rumah, dan sebagainya. Keempat, sumber kebahagiaan. Budaya juga dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seni dan hiburan yang diadakan sesuai dengan tradisi masing-masing masyarakat. Kelima, sumber kekuatan. Budaya dapat menjadi sumber kekuatan bagi suatu masyarakat karena dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara anggotanya (Aurellia, 2023).
Menurut Ndraha (2005), fungsi-fungsi budaya, yaitu : pertama, sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Kedua, sebagai pengikat suatu masyarakat. Kebersamaan adalah faktor pengikat anggota masyarakat yang kuat. Ketiga, sebagai sumber. Budaya merupan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya menghasilkan komoditiekonomi, misalnya: wisata budaya, produk budaya. Keempat, sebagai kekuatan penggerak atau pengubah. Karena budayaterbentuk melalui proses belajar mengajar maka budaya itudinamis dan tidak kaku. Kelima, sebagai kemampuanmembentuk nilai tambah, menghubungkan dengan nilaikeunggulan. Keenam, sebagai pola prilaku. Budaya berisinorma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransisosial. Ketujuh, sebagai warisan, budaya disosialisasikan dandiajarkan kepada generasi berikutnya. Kedelapan, sebagai subtitusi (pengganti) formalisasi, sehingga tanpa diperintah orang akan melakukan tugasnya. Kesembilan, sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan, proses budayadalam pembangunan sebagai perubahan sosial yangberencana. Kesepuluh, sebagai proses yang mempersatukan.Melalui proses value sharing manusia dipersatukan tidakseperti sapu lidi melainkan ibarat rantai. Dan ksebelas, sebagai produk proses usaha mencapai tujuan bersama dalamsejarah yang sama
Perilaku berbudaya dipengaruhi oleh faktor pengasuhan dan lingkungan. Oleh karena itu, interaksi antara masyarakat sangat berkaitan erat dengan perilaku berbudaya (Purwanro, 2010). Perkembangan kebudayaan suatu masyarakat antara lain dipengaruhi oleh : tingkat pendidikan masyarakat; komposisi penduduk/masyarakat; kondisi geografis/wilayah; dan pola interaksi masyarakat dengan dunia luar.
Faktor-faktor di atas hanya merupakan hal pokok yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Tukiman Taruna (Sindhunata, 2000) mengungkapkan empat hal yang terkandung dalam pengembangan masyarakat, yaitu: a. Konsep keswadayaan; b. Inisiatif harus datang dari masyarakat/komunitas sendiri; c. Adanya agen perubahan (pemerintah, LSM, dan sebagainya); d. Adanya pemanfaatan dan pendekatan-pendekatan teknis berbasis pada potensi lokal. John Gillin (Tilaar, 2000) menyampaikan perkembangan kepribadian manusia berbudaya sebagai berikut: a. Kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar. b. Kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi kelakuan tertentu. Jadi kebudayaan merupakan perangsang terbentuknya kelakuan-kelakuan tertentu. c. Kebudayaan mempunyai sistem “reward and punishment” terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. d. Kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar. Pola kehidupan yang dianut pada suatu masyarakat lama kelamaan akan mengendap, mengakar dan mendarah daging hingga akhirnya membudaya menjadi sebuah tatanan yang dianut dan disepakati serta dijunjung oleh masyarakat tersebut.
Melihat betapa pengaruhnya perilaku berbudaya ke dalam kehidupan bermasyarakat, berikut berbagai cara untuk mengamalkannya : pertama, mengembangkan sikap ramah, sopan, santun, dan ramah ketika berinteraksi terutama kepada seseorang yang lebih tua. Kedua, menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh seniman dan budayawan, karena bagaimanapun perilaku berbudaya ini sudah ada sejak turun-temurun dan perlu diwarisi. Ketiga, mulai untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Keempat, mampu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia. Dan kelima, ikut andil dalam melestarikan kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar (Kabar Harian, 2023).
Pembudayaan Perilaku “BISA”
Pembudayaan adalah proses, cara, perbuatan membudayakan (Yusuf, 2002). Pembudayaan dilakukan melalui proses internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi.
Proses melahirkan budaya, termasuk proses pembudayaan perilaku “BISA” umumnya dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu proses internalisasi, proses sosialisasi, dan proses enkulturasi.
Guna mengetahui proses internalisasi, proses sosialisasi, dan proses enkulturasi, Soelaiman (2005) menguarikannya berikut.
Pertama, proses internalisasi. Manusia terlahir dengan potensi bawaan; perasaan, hasrat, nafsu, emosi, dan seterusnya. Sepanjang kehidupan (dari lahir sampai mati) manusia menanamkan dalam kepribadiannya hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan. Individu berusaha memenuhi hasrat dan motivasi dalam dirinya; beradaptasi, belajar dari alam dan lingkungan sosial dan budayanya.
Internalisasi adalah pengaturan ke dalam fikiran atau kepribadian, perbuatan nilai-nilai, patokan-patokan ide atau praktek-praktek dari orang-orang lain menjadi bagian dari diri sendiri (Kartono, 2003).
Pembudayaan atau internalisasi adalah proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Nilai-nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek baik agama, budaya, norma sosial dan lain-lain. Pemaknaan atas nilai inilah yang mewarnai pemaknaan dan penyikapan manusia terhadap diri, lingkungan dan kenyataan di sekelilingnya.
Kedua, proses sosialisasi. Individu belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan sesama, dari individu yang menduduki aneka peranan sosial. Sosialisasi berarti proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Lawang dalam Adlani, 2022). Sosialisasi adalah suatu proses yang dimulai sejak seseorang itu dilahirkan untuk dapat mengetahui dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan, dan pola tingkah laku yang disetujui masyarakat (Wiraatmaja dalam Usman, 2024).
Dalam proses sosialisasi melibatkan agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi, terdapat empat agen sosialisasi yang utama yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan lembaga pendidikan sekolah (Susanto dalam Usman, 2024). Bentuk agen sosialisasi yaitu keluarga, sekolah, kampus, kelompok teman sebaya, media massa, lembaga-lembaga agama, seperti MUI, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RW, RT, Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata, lingkungan tempat tinggal, lembaga adat, partai politik, lembagakemasyarakatan lainnya, dan komunitas-komunitas lainnya baik formal maupun non formal. Salah satu peran agen sosialisasi adalah untuk meningkatkan partisipasi individu di dalam masyarakat melalui pembentukan pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku yang bermakna, seperti Gerakan Kota Bima “BISA”.
Ketiga, proses enkulturasi. Enkulturasi adalah suatu proses bagi seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat. Setelah mempelajari budaya, orang tersebut akan menyesuaikan alam pikirannya dengan kebudayaan lingkungannya (Herskovits dalam Septiarti, dkk., 2017). Enkulturasi adalah proses mempelajari, menginternalisasi, dan mengenkulturasi budaya secara disadari maupun tidak disadari (Hoebel dalam Utami dan Serafica Gischa, 2021). Enkulturasi terus terjadi dari seorang masi bayi hingga kematiannya, sehingga manusia dapat hidup dengan baik serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban milikinya maupun milik orang lain.
Individu mempelajari dan menyesesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma, dan peraturan-peratruran dalam kebudayaannya. Kalau pada awal meniru, sesuai dengan perkembangan kehidupan, ‘membaca’, menghayati, hingga menjadi pola tindakan.
Pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pendidikan juga dipandang sebagai alat untuk perubahan budaya. Proses akulturasi bukan semata-mata transmisi budaya dan adopsi budaya tetapi juga perubahan budaya. Sebagaimana diketahui, pendidikan menyebabkan terjadinya beragam perubahan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi. politik, dan agama. Namun, pada saat yang bersamaan, pendidikan juga merupakan alat untuk konservasi budaya-transmisi, adopsi, dan pelestarian budaya. Mengingat besarnya peran pendidikan dalam proses akulturasi, maka pendidikan menjadi sarana utama pengenalan budaya baru yang kemudian akan diadopsi oleh sekelompok manusia dan kemudian dikembangkan serta dilestarikan. Budaya baru tersebut sangat beragam, mulai dari budaya yang dibawa oleh masing-masing peserta didik dan masing-masing bidang ilmu yang berasal bukan dari budaya setempat, budaya guru yang mengajar, budaya sekolah, dan keluarga.
Enkulturasi tidak akan lepas dari kehidupan manusia, memiliki dua fungsi yaitu untuk sosialisasi nilai dan pembentukan identitas sosial. Enkulturasi disebut sebagai sosialisasi nilai karena enkulturasi mengenalkan budaya yang berlaku pada seorang individu. Dilansir dari Enculturation, enkulturasi mengenalkan norma, nilai, dan praktik budaya dari mulai prosedur kelembagaan hingga perilaku sehari-hari. Fungsi enkulturasi sebagai pembentukan identitas sosial. Pengetahuan akan budaya akan membentuk karakter dan membentuk identitas diri yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Pembentukan identitas diri akan berlaku bagi kebanyakan individu dalam budaya yang sama dan membentuk suatu identitas sosial (Utami dan Serafica Gischa, 2021).
Strategi Dasar
Proses pembudayaan perilaku “BISA” adalah cara atau pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perilaku bersih, indah, sehat dan asri. Meminjam Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan (Burhan, 2020) telah menetapkan tiga strategi dasar promosi kesehatan dan perilaku bersih, indah, sehat dan asri atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Pertama, gerakan pemberdayaan (empowerment)
Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek practice).
Sasaran utama dari pemberdayaan adalah individu dan keluarga serta kelompok masyarakat. Bilamana sasaran sudah pindah dari mau ke mampu melaksanakan boleh jadi akan terkendala oleh dimensi ekonomi. Dalam hal ini kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan langsung, tetapi yang sering kali dipraktikkan adalah dengan mengajaknya ke dalam proses pengorganisasian masyarakat (community organization) atau pembangunan masyarakat (community development). Untuk itu sejumlah individu yang telah mau dihimpun dalam suatu kelompok untuk bekerjasama memecahkan kesulitan yang dihadapi. Tidak jarang kelompok ini pun masih juga memerlukan bantuan dari luar (misalnya dari pemerintah atau dari dermawan). Disinilah letak pentingnya sinkronisasi promosi kesehatan dan PHBS dengan program kesehatan yang didukungnya.
Kedua, bina suasana (social support)
Bina suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial dimanapun ia berada (keluarga di rumah, orang-orang yang menjadi panutan/idolanya, kelompok arisan, majelis agama, dan bahkan masyarakat umum) menyetujui atau mendukung perilaku tersebut. Oleh karena itu, untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat khususnya dalam upaya meningkatkan para individu dari fase tahu ke fase mau, perlu dilakukan Bina Suasana. Terdapat tiga pendekatan dalam bina suasana yaitu: pendekatan individu, pendekatan kelompok, dan pendekatan masyarakat umum.
Ketiga, pendekatan pimpinan (advocacy).
Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (stakeholders). Pihak-pihak yang terkait ini bisa brupa tokoh masyarakat formal yang umumnya berperan sebagai penentu kebijakan pemerintahan dan penyandang dana pemerintah. Juga dapat berupa tokoh-tokoh masyarakat informal seperti tokoh agama, tokoh pengusaha, dan yang lain yang umumnya dapat berperan sebagai penentu “kebijakan” (tidak tertulis) dibidangnya dan atau sebagai penyandang dana non pemerintah. Perlu disadari bahwa komitmen dan dukungan yang diupayakan melalui advokasi jarang diperoleh dalam waktu yang singkat. Pada diri sasaran advokasi umumnya berlangsung tahapan-tahapan yaitu: a) mengetahui atau menyadari adanya masalah, b) tertarik untuk ikut mengatasi masalah, c) peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah, d) sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif pemecahan masalah, dan e) memutuskan tindak lanjut kesepakatan.
Hal-hal yang mempengaruhi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ada dua yakni faktor intern, dan faktor ekstern (faktor lingkungan). Faktor intern, sebagian terletak di dalam diri individu itu sendiri. Misalnya, keturunan. Seseorang berperilaku tertentu karena memang sudah demikianlahditurunkan dari orangtuanya. Sifat-sifat yang dimilikinya adalahsifat-sifat yang diperoleh dari orang tua atau neneknya dan lainsebagainya.
Selain, faktor keturunan, maka faktor lain yang berpengaruh yakni motif. Manusia berbuat sesuatu karena adanya dorongan atau motif tertentu. Motif atau dorongan ini timbul karena dilandasi oleh adanya kebutuhan, baik kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan rohani.
Sedangkan faktor ekstern (faktor lingkungan), sebagian terletak di luar dirinya yang mempengaruhi individu sehingga di dalam diri individu timbul unsur-unsurdan dorongan untuk berbuat sesuatu.
Faktor yang Mempengaruhi Perilaku
Perilaku dari segi biologis adalah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan, jadi perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kegiatan manusia itu sendiri sering tidak teramati dari luar manusia itu sendiri, misalnya: berpikir, persepsi, emosi, dan sebagainya. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2007).
Perilaku merupakan manifestasi dari kehidupan psikis. Perilaku yang ada pada individu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu tersebut. Perilaku merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang ada sedangkan respon merupakan fungsi yang tergantung pada stimulus dan individu (Wood worth & Schlosberg dalamWalgito, 2010).
Perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati bahkan dapat dipelajari (Robert Kwik dalam Mubarak, 2006). Perilaku tidak sama dengan sikap. Sikap adalah hanya sesuatu yang lebih cenderung untuk mengadakan tindakan terhadap suatu objek dengan suatu cara yang mengatakan adanya tanda-tanda untuk senang atau tidak senang pada objek tersebut (Mubarak, 2006).
Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku, menurut Lawrence Green (Notoatmodjo, 2007). Pertama, faktor-faktor pemudah (predisposing factors). Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Faktor-faktor ini terutama yang positif mempermudah terwujudnya perilaku, maka sering disebut faktor pemudah.
Kedua, faktor-faktor pemungkin (enambling factors).Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, lingkungan fisik misalnya: air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja, ketersediaan makanan yang bergizi, dan sebagainya. Termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti: puskesmas, rumah sakit, poliklinik, posyandu, polindes, pos obat desa, dokter atau bidan praktek swasta, dan sebagainya. Untuk berperilaku sehat, masyarakat memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor-faktor ini disebut faktor pendukung atau faktor pemungkin.
Ketiga, faktor pendorong (reinforcing factors).Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para petugas kesehatan. Termasuk juga disini undang-undang, peraturan-peraturan, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan. Dalam perilaku sehat, masyarakat kadang-kadang bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif dan dukungan fasilitas saja, melainkan diperlukan perilaku contoh (acuan) dari para tokoh kesehatan. Di samping itu undang-undang juga diperlukan untuk memperkuat perilaku masyarakat tersebut.
Filosofi Tiga “Mulai” Menuju Perubahan
Keberhasilan perubahan, termasuk mewujudkan Kota Bima “BISA”, harus diawali dengan filosofi tiga “mulai”. Apa itu? Yakni (1) mulai dari diri sendiri (start with yourself), (2) mulai dari hal-hal yang kecil (start small), dan (3) mulailah sekarang (start now), jangan menunggu-nunggu atau lakukan sedini mungkin (start early) (Usman, 2024).
Mulai Dari Diri Sendiri
Pertama, mulai dari diri sendiri. Ketika kita tidak mampu lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri (Viktor Frankl). Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri (Leo Tolstoy) (Usman, 2024).
Perubahan dan pembenahan terhadap diri sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai profesi merupakan titik sentral yang harus dimulai. Setiap orang umumnya selalu memiliki cita-cita. Bahkan tidak sedikit orang yang mengiringi cita-citanya dengan do’a, agar hidup dengan kebaikan (hasanah) di dunia dan di akhirat. Tetapi, bertumpu kepada do’a saja tentu tidak cukup. Karenanya, setiap manusia perlu mengetahui dan memulai untuk dapat mencapai perubahan menuju hasanah yang diinginkan. Perubahan seseorang, dimulai dari perubahan dalam dirinya. Kalau pikirannya berubah dan ia melakukan perubahan itu secara berkelanjutan.
Bagus sekali Walter Doyle Staples (Usman, 2024),menulis dalam kalimat yang puitis namun penuh tenaga. Bila engkau mengubah pikiranmu, maka engkau mengubah keyakinanmu. Bila engkau mengubah keyakinanmu, maka engkau mengubah harapanmu. Bila engkau mengubah harapanmu, maka engkau mengubah sikapmu. Bila engkau mengubah sikapmu, maka engkau mengubah perilakumu. Bila engkau mengubah perilakumu, maka engkau mengubah penampilanmu. Bila engkau mengubah penampilanmu, maka engkau mengubah hidupmu.
Rhenal Kasali (2015) memperkenalkan lima sifat yang perlu dimiliki seseorang agar orang itu dapat mengembangkan perubahan yang positif di dalam dirinya.
Karena melihat + karena mengalami. Pertama, O = openness to experience. Terbuka pikiran
hati + telinga. Kedua, C = conscientiousness. Terbuka. Ketiga, E = extrovertness. Terbuka pada orang lain. Keempat, A = agreeableness. Terbuka pada kesempatan. Kelima, N = neuroticism. Terbuka terhadap berbagai tekanan.
Orang ini dapat : sabar, tabah, teguh, konsisten pada tujuan hidupnya.
Mulai dari diri sendiri. John Maxwell mengatakan, “Di kala kita bodoh, kita memang ingin menguasai orang lain, tetapi kala kita bijak, kita ingin menguasai diri sendiri.” “Semua orang ingin mengubah dunia, tetapi mereka lupa mengubah atau menguasai diri mereka sendiri”, demikian Leo Trostoy. Walt Emerson menyatakan hal senada bahwa, “Yang ada di belakang dan yang di depan tidak ada artinya dibanding dengan yang terdapat di dalam dirinya”, dan “cepat atau lambat, pemenang adalah mereka yang menganggap diri mereka bisa” (Aswandi dalam Usman, 2024).
Beberapa faktor yang mempengaruhi diri seseorang untuk memulai perubahan adalah pikiran dan sikap atau perasaan. Mahatma Ghandi selalu mengingatkan, ”Perhatikan pikiranmu, karena ia akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu karena ia akan menjadi perilakumu. Perhatikan perilakumu karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena ia akan menjadi karaktermu, dan perhatikan karaktermu karena ia akan menjadi taqdirmu.”
Pendapat yang sama disampaikan Harun Yahya (2002) dalam bukunya “Ever Thought about The Truth”. Ia menjelaskan bahwa “Dunia yang kita ketahui sebenarnya adalah dunia di dalam pikiran kita di mana ia didesain, diberi suara dan warna atau dunia yang diciptakan oleh pikiran kita”. Stephen Hawking (2010) bapak teori relativitas dalam bukunya ”The Grand Design” mengatakan bahwa ”Tiada konsep realitas (kenyataan) yang independen dari gambaran atau teori yang ada dalam pikiran atau persepsi kita.” Demikian pula, John Kehoe (2012) dalam bukunya ”Mind Power” bahwa pikiran menciptakan realitas. Segala peristiwa dipengaruhi dari apa yang kita bayangkan, kita visualisasikan, kita hasratkan, kita inginkan atau kita takutkan, serta mengapa dan bagaimana gambar yang ditetapkan dalam pikiran bisa dibuat menjadi kenyataan.
Namun dalam kenyataan hidup ini, seseorang tidak tepat waktu dalam menggunakan pikirannya untuk memulai perubahan sebagaimana disinyalir oleh Peter F. Drucker bahwa kesalahan berpikir seringkali terjadi ketika kita berpikir tentang masa depan kita dengan cara berpikir kemarin. “Bukti lain, pikiran kita hingga saat ini belum tersekolahkan”, demikian Gardner (2012) dalam bukunya The Unschooled Mind. How childern thing and how school should tesch. Selain pikiran, faktor diri yang sangat mempengaruhi saat memulai perubahan adalah sikap dan perasaan. Kotter dan Cohen (2014) dalam bukunya “The Heart of Change” menambahkan bahwa jantung perubahan bukan berada dalam pikiran, melainkan pada “sikap atau perasaan”. Dikatakan, “Orang mengubah apa yang mereka lakukan bukan karena mereka diberi analisis yang mengubah pikiran mereka, namun lebih karena mereka ditunjukkan sebuah kebenaran yang mempengaruhi perasaan mereka”. Tantangan tunggal terbesar dalam setiap perubahan adalah mengubah sikap. Kunci dan pergeseran sikap tersebut tampak jelas dalam transformasi yang sukses, tidak terlalu banyak kaitannya dengan analisis dan pertimbangan, namun lebih cenderung terkait dengan melihat dan merasakan.
Mulai Dari Hal-hal Kecil
Kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. Perubahan yang besar tidak akan pernah berhasil, kalau tidak dimulai terhadap hal-hal yang kecil. Mulailah dari hal yang kecil untuk merubah hal yang besar. Seribu langkah, dimulai dari langkah pertama. Sukses adalah akumulasi dari usaha-usaha kecil, yang dilakukan secara berulang-ulang (Collier dalam Subair, 2020). Kata orang bijak, langkah-langkah kecil akan menentukan langkah-langkah besar. Mulailah dengan rencana kecil, sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, namun membuat kita dan sekeliling kita tumbuh. Perubahan tidak dapat dilakukan seketika menjadi lompatan besar, melainkan harus dimulai dengan hal-hal kecil di sekitar kita.
Kasali (2007) dalam bukunya “Re-Code Your Change DNA” mengatakan bahwa dunia berubah bukan dimulai dengan banyak orang, tetapi selalu dimulai dari sedikit orang. Nabi Muhammad SAW bersama empat orang khalifah (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali) dalam waktu 20 tahun mampu merubah peradaban Arab dari biadab menjadi beradab. Demikian pula Nabi Isa As bersama tujuh orang rasulnya mampu membuat perubahan besar pada zamannya. Menjadi tidak aneh, jika Bung Karno diawal kemerdekaan mengatakan, “Serahkan kepadaku sepuluh orang pemuda, akan kuubah Indonesia ini.”
Uraian di atas mendapat penguatan dari Hukum Pareto atau Hukum 20/80 yang diperkenalkan oleh Vilvredo Pareto, yakni yang sedikit (20%) akan memberi hasil yang terbesar (80%). Berdasarkan hukum ini menunjukkan segala hal kecil, berbiaya kecil, dan dengan jumlah terbatas mampu memberi dampak yang luar biasa. Gladwell (2010) dalam bukunya “Triping Point” menegaskan bahwa,”how little thing can make a big difference”.
Friel & Friel (2015) mengatakan hal yang sama bahwa “satu perubahan kecil yang dilakukan secara konsistem dan dengan integritas, benar-benar bisa mengubah keseluruhan sistem.” Dalam banyak pendapat dikatakan bahwa ”tidak jarang kelompok kecil mampu atau dapat mengalahkan kelompok besar karena kelompok kecil itu terorganisir dengan baik.”
Tidak hanya itu, jika kita memulai perubahan dari hal-hal yang kecil, kemudian ternyata gagal melakukan perubahan itu, maka perubahan yang gagal tersebut tidak memberi dampak yang merusak keseluruhan sistem yang ada, dan bahkan kegagalan itu menjadi pembelajaran yang bermakna bagi perubahan yang lebih besar. Orang bijak mengatakan, ”Jika kita tidak segera menangani atau menyelesaikan perkara-perkara kecil, maka kitapun tak akan mampu menangani atau menyelesaikan perkara-perkara besar” dan ”Banyak orang yang tidak menyadari bahwa setiap kerusakan nilai-nilai selalu dimulai dari hal-hal kecil”. Sebaliknya, sering terjadi kegagalan dalam memulai perubahan karena suka meributkan hal-hal kecil.
Mulailah Sekarang, Jangan Menunggu
Ketiga, mulailah sekarang, jangan menunda-nunda. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali, lebih baik sekarang daripada harus menunggu-nunggu terus. Kesempatan tidak akan datang dua kali dengan tawaran yang sama. Harus diakui siapapun kita, punya kebiasaan buruk. Belajar di hari terakhir sebelum ujian, dan berpikir keras sesaat sebelum keputusan diambil. Di Meksiko, orang-orang berperangai buruk dikenal sebagai penganut “mania (besok) principle.” “Kalau bisa dipikirkan besok, mengapa harus dikerjakan hari ini.” Nyatanya, hidup mereka tak pernah sejahtera.
Marilah kita mengeksplorasi sebab-sebab penundaan yang paling sering muncul, di antaranya. Pertama, stres. Saat seseorang stres, kuatir, cemas atau gelisah, maka sangatlah susah untuk bisa bekerja dengan produktif. Dalam situasi tersebut menunda seringkali menjadi salah satu pilihan yang sering diambil. Kedua, terjebak dalam tumpukan tugas dan jadwal. Ketiga, rasa malas. Terkadang seseorang menunda karena terlalu letih secara fisik dan emosi. Akibatnya kita mengambil waktu untuk istirahat sejenak, dan di sinilah jebakannya. Keempat, kurangnya motivasi. Kelima, kurangnya disiplin. Keenam, buruknya manajemen diri karena kebiasaan buruk. Ketujuh, kurangnya keterampilan yang dibutuhkan. Dan kedelapan, perfeksionis. Salah satu sebab penundaan yang cukup sering adalah ingin perfeksionis yaitu keinginan untuk melakukan segala sesuatu setelah semuanya sempurna yang akhirnya membuat kita menunda melakukan rencana-rencana kita untuk menunggu ‘waktu yang tepat’ (Anonymous dalam Usman, 2024).
Semua orang ingin berubah, tetapi sedikit orang yang melakukannya karena alasan yang sama, yakni sulit memulainya. Kemampuan individu dan institusi menerima, merespons dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi menjadi kunci terpenting bagi mereka yang memulai dan berhasil melakukan perubahan.
Dari berbagai penelitian dan kajian mendalam secarakomprehensif, Arnold Toynbee (Subair, 2020) menyimpulkan bahwa “Kebangkitan (berubah, maju dan sejenisnya) umat manusia ini bergantung pada kemampuannya merespons atau menanggapi secara cepat, tepat atau akurat dan pantas terhadap tantangan atau masalah yang dihadapinya.”
Orang sukses adalah orang yang segera melaksanakan idenya, tidak menunggu atau menunda pekerjaannya karena suka menunda pekerjaan terbukti 64% menjadi faktor kegagalan”, demikian Frans Bruno. Albert Einstein kembali menasehati melalui kalimat pendek, ”Ideas and than action”, artinya jika ada ide, maka segera ambil tindakan. Maxwell menambahkan, ”kesalahan terbesar yang diperbuat seseorang adalah tidak berbuat apa-apa”. Sudah tepat jika mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ”Kerja, Kerja, Kerja” karena bangsa ini memerlukan manusia gesit dan cepat bertindak. Dikatakan, ”Tidak peduli seberapa jauh jalan salah yang Anda jalani, putar arah sekarang juga”, demikian Kasali (2010) dalam bukunya berjudul ”Change !”.
Efek kupu-kupu (bahasa Inggris: butterfly effect) adalah istilah dalam “Teori Chaos” (Chaos Theory) yang berhubungan dengan “ketergantungan yang peka terhadap kondisi awal” (sensitive dependence on initial conditions), di mana perubahan kecil pada satu tempat dalam suatu sistem non-linear dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam keadaan kemudian. Istilah yang pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lorenz ini merujuk pada sebuah pemikiran bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Fenomena ini juga dikenal sebagai sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap kondisi awal. Perubahan yang hanya sedikit pada kondisi awal, dapat mengubah secara drastis kelakuan sistem pada jangka panjang. Jika suatu sistem dimulai dengan kondisi awal misalnya 2, maka hasil akhir dari sistem yang sama akan jauh berbeda jika dimulai dengan 2,000001 di mana 0,000001 sangat kecil sekali dan wajar untuk diabaikan. Dengan kata lain: kesalahan yang sangat kecil akan menyebabkan bencana dikemudian hari. ?
Kalau Bukan Kita Siapa Lagi. Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi
Gerakan Kota Bima “BISA” mesti dibudayakan. Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi.
Menarik puisinya Cak Bejo. Siapa lagi kalau bukan kita/Yang bangkit di kala malam buta/Menggenggam api di tangan kiri/Menyalakan obor dalam sepi.
Siapa lagi kalau bukan kita/Yang merangkai mimpi jadi nyata/Menapak jejak di tanah kering/Menyirami harap di musim gersang.
Dan kapan lagi kalau tidak sekarang/Saat fajar masih mengintip di balik bukit/Saat angin masih berbisik lembut/Menyapa dedaunan yang mulai tersadar.
Dan kapan lagi kalau tidak sekarang/Menyulam waktu dengan benang keberanian/Menggubah lagu dalam irama perjuangan/Menari di atas panggung kehidupan yang fana.
Siapa lagi kalau bukan kita/Yang menabur benih cinta di ladang kemanusiaan/Yang menenun kain persaudaraan/Menghapus batas, meruntuhkan dinding kebencian.
Dan kapan lagi kalau tidak sekarang/Saat hati masih penuh tekad membara/Saat jiwa masih bebas melayang tinggi/Menggapai bintang/meraih pelangi di ujung harapan.
Siapa lagi kalau bukan kita/Dan kapan lagi kalau tidak sekarang/Mari bersama kita ukir sejarah/Dengan tinta emas di lembaran takdir/Membingkai dunia dengan kasih dan asa.
Semoga bermanfaat !
*Dosen Universitas Mbojo Bima (Alumni UNM dan UNHAS Makassar)