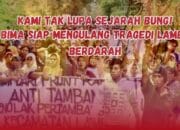Oleh : Ahmad Usman*
Dosen Universitas Mbojo Bima (Alumni UNM dan UNHAS Makassar). Foto: Ist
Kahaba.Net (21 Juni 2025) mengangkat berita dengan judul “Aksi Nyata Dukung Program BISA, Holly Mart, FKGK dan TNI Gotong Royong Bersihkan Kawasan Amahami.” Dalam rangka mendorong program prioritas Pemerintah Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri), Holly Mart bersama TNI, Forum Komunikasi Gereja Kristen (FKGK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kementerian Agama, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi bakti sosial membersihkan sampah di kawasan Pantai Amahami, Masjid Terapung dan area sekitar Pasar Amahami, Sabtu 21 Juni 2025.
Sebelumnya juga, Kahaba.Net (13 Juni 2025) mengusung berita dengan judul “Pemkot Bima Galakkan Gerakan BISA Lewat Aksi Gotong Rotong Lingkungan.”Mengutip penjelasan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, bahwa Gerakan BISA bukan sekadar slogan, melainkan harus dihayati sebagai bagian dari budaya dan kesadaran kolektif. Program BISA harus benar-benar diimplementasikan dengan hati yang ikhlas. Ini bukan sekadar rutinitas, tapi menjadi bentuk kepedulian dan amal nyata bagi lingkungan serta masa depan generasi kita.
Beberapa media lokal mengangkat tema yang sama tentang gotong royong, meski redaksi judul yang berbeda. Misal : Keren, Inilah Aksi Nyata Mahasiswa STKIP Taman Siswa, Dukung Program Kota Bima BISA; GOW Gandeng DLH Kota Bima Gelar Aksi Gotong Royong dan Penataan Taman Paruga Nae, Dukung Gerakan “Kolaborasi Hijau” Menuju Kota Bima BISA; Dorong Gerakan BISA, Pemerintah Kota Bima Ikuti Kegiatan “Gotong Royong Bersama” Dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bima; Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima Pimpin Kegiatan Gotong Royong dalam Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025: “Bentuk Komitmen BISA”; Pemkot Bima Gotong Royong Wujudkan Gerakan Kota Bima BISA; Gerakan Bersih Kota Bima : Wali Kota & ASN Turun Tangan Wujudkan Lingkungan Sehat; Wakil Wali Kota Bima Pimpin Aksi Bakti Sosial dan Pembersihan Teluk dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup 2025; dan sejumlah berita-berita lainnya yang intinya adalah revitalisasi budaya gotong royong yang akhir-akhir ini mulai terdegradasi dan tergerus.
Gotong royong tidak hanya menjadi sebuah jargon tanpamakna, tapi harus menjadi sebuah nilai yang mengejawantah dalam bentuk semangat (spirit) yang berbasis pada kolektivisme atau rasa kebersamaan dalam berupaya bersama demi kepentingan dan tujuan bersama, lepas dari sekat-sekatsukuisme, kelas sosial, kepentingan sektoral maupun politikpraktis (Usman, 2024).
Statemen di atas mengisyaratkan bahwa gotong royong, sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, tidak boleh hanya menjadi slogan kosong tanpa makna. Lebih dari sekadar kata-kata, gotong royong harus menjelma menjadi spirit atau semangat yang hidup dalam tindakan nyata. Semangat ini didasarkan pada: pertama, kolektivisme. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kedua, kebersamaan. Bekerja bersama-sama, saling membantu, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, lepas dari sekat-sekat. Gotong royong harus mampu mengatasi perbedaan suku, kelas sosial, kepentingan sektoral (misalnya, kepentingan bisnis atau organisasi tertentu), dan politik praktis (AI, 2025). Gotong royong bukan sekadar kerja bakti atau membantu membangun infrastruktur. Lebih dalam dan luas dari itu. Gotong royong merupakan semangat persatuan dan solidaritas yang mendorong masyarakat untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mencapai kemajuan bersama, terlepas dari perbedaan yang ada.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, itulah sebuah peribahasa yang mengandung nilai sakral dalam membangun kebersamaan yang diwujudkan dengan gotong royong. Gotong royong merupakan paham dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Sebab konsep gotong-royong ini menggambarkan suatu usaha, satu amal, satu pekerjaan secara bersama-sama. Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-bantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua kebahagiaan semua (Felix dalam Usman, 2019). Untuk membangun peradaban sebuah bangsa harus dilakukan dengan membangun budi pekerti serta membangkitkan semangat kebersamaan.
Gotong royong adalah salah satu budaya bangsa yang membuat Indonesia, dipuji oleh bangsa lain karena budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia.Ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat Indonesia bisa bersatu dari Sabang hingga Merauke, walaupun berbeda agama, suku dan warna kulit.
Kita bisa mengembangkan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih cerdas (smart community) melalui gotong royong. Budaya gotong royong tidak berarti harus selalu melakukan hal-hal besar bagi masyarakat. Dengan melakukan kegiatan sederhana pun, seperti membagikan pakaian bekas kepada masyarakat yang membutuhkan, melakukan pembersihan lingkungan, mendorong terciptanya kerjasama antar warga dan menanam pohon, yayasan telah melakukan pelayanan yang baik bagi masyarakat (Hafid, 2020).
Harus diakui bahwa dalam khazanah kehidupan masyarakat Indonesia, istilah gotong royong menempati posisi terhormat, membumi bahkan berakar. Terhormat karena istilah tersebut sering dijadikan kata kunci oleh para tokoh bangsa untuk menggalang dukungan terhadap suatu gagasan. Presiden Ir. Soekarno menggunakan term gotong royong sebagi kata lain Ekasila yang merupakan perasan lanjutan dari Trisila setelah sebelumnya merupakan hasil peras dari Pancasila. Pada era Presiden Soeharto dengan Orde Barunya, kata gotong royong juga sering dijadikan kata kunci dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan. Betapapun besar anggaran yang disediakan negara melalui APBN bila tanpa didukung semangat kebersamaan bernama gotong royong dalam membangun dan memelihara hasil pembangunan, tentulah program itu tidak akan berjalan secara sangkil dan mangkus (efektif dan efisien). Di era pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, gotong royong bahkan digunakan sebagai nama kabinet. Pemberian nama Kabinet Gotong Royong merupakan gambaran bahwa pemerintahan saat itu dijalankan secara kolektif dengan merangkul berbagai kekuatan politik untuk bekerjasama dengan semangat kebersamaan.
Lebih jauh Nasroen, salah seorang pelopor kajian filsafat Indonesia menyatakan bahwa gotong royong merupakan salah satu dasar filsafat Indonesia. Nasroen (1907-1968) Guru Besar Filsafat di Universitas Indonesia dalam bukunya “Falsafah Indonesia”, mengatakan bahwa gotong royong adalah dasar Falsafah Indonesia. Dengan kata lain bahwa gotong royonglah yang menjadi ciri utama manusia Indonesia pada umumnya. Dari ribuan tahun silam Indonesia telah menciptkan konsep ini. Kita bisa melihat di ritual-ritual keagamaan di sana yang masih animisme dan dinamisme (Salamah , 2022).
Gotong royong bukan “barang baru”. Setiap sukubangsa mengenalnya dengan istilah yang berbeda. Orang Batak menyebutnya “Dalihan Na Tolu”; Orang Makassar menyebutnya “Mapalus”; Orang Lampung menyebutnya “Nemui Nyimah”; Orang Trunyan (Bali) menyebutnya “Sekaha”; Orang Kepulauan Kei (Maluku Tenggara) menyebutnya “Masohi”; Orang Jawa menyebutnya “Sambatan”; dan masih banyak sebutan lain yang ditujukan kepada gotong-royong, mengingat jumlah sukubangsa yang ada di Indonesia, baik yang sudah maju maupun yang masih diupayakan untuk berkembang (masyarakat terasing), lebih dari 500 sukubangsa (Melalatoa, 1985).
Laksono (2009) menyebutkan bahwa istilah gotong-royong baru tertulis dalam sebuah Kamus Bahasa Jawa 1983. Meskipun demikian, menurutnya gotong-royong sebagai praktek sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Bayangkan saja bagaimana mungkin bangunan-bangunan megalitik di Nias, Sumba, dan berbagai tempat lainnya dapat terwujud kalau tanpa ada gotong-royong? Bayangkan juga bagaimana batu-batu besar itu dapat disusun dan diukir menjadi candi di puncak Gunung Dieng, Borobudur, dan Prambanan? Juga, bagaimana kerajaan-kerajaan kita dapat ditegakkan kalau tanpa pengupahan (kalau tidak ada gotong-royong). Oleh karena itu, tidak berlebihan jika gotong-royong menjadi salah satu identitas (jatidiri) bangsa Indonesia. Bahkan, salah seorang proklamator kemerdekaan (Soekarno) di masa Orde Lama sempat mengkristalkan bahwa inti Pancasila adalah gotong-royong (Ahimsa-Putra, 2008 dan Laksono, 2009).
Makna Gotong Royong
Dalam telaah sosiologi, gotong royong diidentikkan ataudianggap sama dengan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah keseluruhan keyakinan dan perasaan yang membentuk sistem tertentu dan dimiliki bersama. Kesadaran kolektif memiliki sifat sakral karena mengharuskan rasa hormat dan ketaatan, hal tersebut dapat tercipta dengan baik apabila perilaku individu dalam kelompok masyarakat telah sesuai dengan sistem yang ada (Khaldun dalam Soekanto, 2013).
Ada juga penggiat yang menerjemahkan kata GOTONG ROYONG sebagai sebuah akronim. G = Giatkan kegiatan menjaga lingkungan dengan membangun Pos Kamling, O = Orang bijak tahu hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, T = Tak ada kata “sulit” jika jumlah kita tak sedikit, O = Olahragakan masyarakat dengan kegiatan kebersihan lingkungan, N = Niat dan tekad yang besar menguatkan persatuan, dan G = Gerakan kebersihan lingkungan harus ditingkatkan. Kemudia, R = Rasa cinta tanah air dapat dipupuk dengan gotong royong, O = Ojohdumeh tansah eling lan waspada, Y = Yang selalu bersatuakan lebih maju, O = Organisasikan warga dengan saling membantu, N = Negara dan bangsa harus bersatu padu, dan G = Galang pesatuan dengan gotong royong (Usman, 2024).
Nilai, Prinsip, dan Pokok-pokok Aktivitas Gotong Royong
Gotong-royong sesungguhnya adalah suatu nilai. Sebagai suatu nilai, gotong-royong baru dapat diamati setelah terwujud dalam aspek tingkah laku. Misal, ada orang-orang yang bersama-sama mengerjakan sesuatu dengan tujuan tertentu yang merupakan kepentingan bersama (Widodo, 2011).
Jika dilihat sekilas, gotong royong tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal yang mudah dan sederhana. Namun dibalik kesederhanaannya tersebut, gotong royong menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat. Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain: kebersamaan, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, tolong menolong, sosialisasi, kekeluargaan, keadilan, sukarela (tanpa pamrih), tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat.
Nilai kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama.
Nilai persatuan dan kesatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyakarat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul.
Nilai rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama.
Nilai tolong menolong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain.
Nilai sosialisasi. Di era modern, kehidupan masyarakat cenderung individualis. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah maskhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya.
Dengan nilai-nilai yang terkandung tersebut, mestinya budaya gotong royong dapat menjadi “suplemen” sekaligus “obat” untuk berbagai “penyakit” yang melanda bangsa ini, termasuk penyakit yang melanda sistem birokrasi di Indonesia. Gotong royong harus dimaknai secara luas dan mendalam, tidak hanya sebatas gotong royong membuat jembatan, mendirikan mushola, membersihkan saluran air, ataupun kegiatan-kegiatan fisik lainnya.
Hubungannya gotong-royong sebagai nilai budaya, maka Bintarto (Usman, 2024) mengemukakan, nilai itu dalam sistem budaya orang Indonesia mengandung empat konsep, yakni: pertama, manusia itu tidak sendiri di dunia ini tetapi dilingkungi oleh komunitinya, masyarakatnya dan alam semesta sekitarnya. Di dalam sistem makrokosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu. Kedua, dengan demikian, manusia pada hakekatnya tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya. Ketiga, karena itu, ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa. Keempat, selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dengan sesamanya dalam komuniti, terdorong oleh jiwa sama tinggi sama rendah.
Nilai-nilai dan norma masyarakat dihasilkan dari proses interaksi sosial. Interaksi sosial antara daerah satu dengan yang lain menghasilkan pola yang berbeda. Pola yang brebeda menjadi ciri khas tersendiri di suatu daerah. Di pedesaan masyarakat mengandalkan gotong-royong untuk mengerjakan sesuatu yang berat, misalnya membangun jembatan, rumah, tempat ibadah dan sebagainya. Gotong-royong terpelihara karena proses interaksi saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hubungan timbal balik seseorang akan bergantian membutuhkan tenaga bantuan orang lain.
Gotong royong adalah sebuah prinsip. Prinsip adalah hukum, tidak bisa tidak, harus seperti itu. Prinsip adalah panduan yang mengompasi hidup Anda untuk kembali ke diri sejati Anda (Qodri Azizy dalam Poerwanto, 2012). Prinsipadalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak (Tumanggo, 2012).
Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu. Prinsip dari kegiatan gotong royong, sebagai berikut: pertama, kegiatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang merupakan anggota suatu kesatuan desa, kampung, pelajar suatu sekolah. Organisasi tertentu dan sebagainya. Kedua, keikutsertaannya berdasarkan atas kesadaran bahwa kegiatan itu demi kepentingan sesama anggota sebagai kesatuan/keluarga. Ketiga, tidak ada perasaan terpaksa ataupun didorong pamrih apapun kecuali ingin menolong sesama warga. Keempat, keikutsertaan spontan(Ulum, dkk., 2022).
Alasan pentingnya gotong royong, yaitu: pertama, manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Kedua, Manusia baru berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesamanya. Ketiga, Manusia sebagai mahluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihi dan tenggang rasa terhadap sesamanya. Keempat, dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan setiap manusia untuk bekerjasama, bergotong royong dalam mencapai kesehjahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan kelima, usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadikan suatu kegiatan terasa lebih ringan, mudah dan lancar (Dewanti, dkk., 2023).
Manfaat gotong royong bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara. Di antara manfaat gotong rotong, yakni :meringankan beban pekerjaan, waktu dan biaya yang harus ditanggung; menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat; menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antarwarga masyarakat; meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama; menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan; dan mempertinggi ketahanan bersama (Saragih, 2025).
Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Semakin banyak orang yang terlibat dalam usaha membangun atau membersihkan suatu lingkungan, maka akan semakin ringan pekerjaan dari masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Selain meringankan pekerjaan yang harus ditanggung oleh masing-masing individu, gotong royong juga membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat untuk diselesaikan. Artinya, gotong royong dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.
Gotong royong memiliki nilai-nilai yang menjadikan gotong royong menjadi budaya yang sangat baik untuk dipelihara. Gotong royong dapat menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Masyarakat yang mau melakukan gotong royong akan lebih peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka rela untuk saling berbagi dan tolong menolong. Masyarakat juga dapat lebih “guyup” karena gotong royong menjaga kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota yang ada di masyarakat.
Menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antarwarga masyarakat. Lingkungan yang harmonis akan menyehatkan masyarakatnya. Ketika ada satu anggota masyarakat yang kesulitan, maka anggota masyarakat lain akan sigap memberikan pertolongan. Hubungan sosial yang baik dan harmonis seperti ini dapat dibangun jika masyarakat mau melakukan kegiatan gotong royong. Gotong royong dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik pada masyarakat. Sebagai akibatnya, hubungan antar anggota masyarakat pun akan semakin harmonis.
Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Dalam skala yang lebih besar, gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat yang sudah solid di tingkat RT, RW, Dusun akan mampu menjalin persatuan yang lebih besar lagi dalam skala nasional. Gotong royong mampu menyadarkan masyarakat jika kita semua berada di tanah air yang sama, sehingga sikap persatuan dan kesatuan yang ada juga harus diwujudkan dari Sabang sampai Merauke, yakni pada seluruh daerah di Indonesia.
Pokok-pokok aktivitas gotong royong mengandung unsur-unsur : usaha atau kegiatan kerja bersama; setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing; berdasarkan keikhlasan dan sukarela; tanpa pamrih (tanpa harapan balas jasa); dan kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama.
Manfaat Budaya Gotong Royong
Manfaat dari gotong-royong bagi masyarakat adalah dapat mengembangkan atau menciptakan rasa kebersamaan antar masyarakat yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lainnya, sehingga gotong-royong ini tidak selamanya perlu dibentuk kepanitiaan secara resmi melainkan cukup adanya pemberitahuan pada warga komunitas mengenai kegiatan dan waktu pelaksanaannya, kemudian pekerjaan dilaksanakan setelah selesai bubar dengan sendirinya.
Keuntungan dari manfaat gotong royong, yaitu: pertama, pekerjaan menjadi mudah dan ringan dibandingkan apabila dilakukan secara perorangan; kedua, dapat memperkuat dan mempererat hubungan antar warga masyarakat di mana mereka berada bahkan dengan kerabatnya yang telah bertempat tinggal di tempat lain; ketiga, dapat menyatukan seluruh warga masyarakat yang terlibat di dalamnya; keempat, gotong-royong dapat dilakukan untuk meringankan pekerjaan di lahan pertanian; kelima, dapat meringankan pekerjaan di dalam acara yang berhubungan dengan pesta yang dilakukan salah satu warga masyarakat; dan keenam, serta bahu membahu dalam membuat dan menyediakan kebutuhan bersama (Anggorowati dan Sarmini, 2015).
Gotong-royong sudah tidak dapat dipungkiri lagi sebagai ciri bangsa Indonesia yang turun–temurun, sehingga keberadaannya harus dipertahankan. Gotong-royong adalah salah satu contoh pola perilaku yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ternyata gotong royong memiliki beberapa manfaat (Widiastuti, dkk., 2022).
Pertama, pekerjaan cepat selesai. Bekerja sendirian, tentu akan lebih lama jika dibandingkan dengan bekerja sama dengan banyak orang. Sebagai contoh pada saat menggali selokan yang mampet, bila dilaksanakan oleh satu orang mungkin 2 atau 3 hari baru selesai. Akan tetapi jika dikerjakan oleh seluruh warga kampung mungkin akan selesai dalam waktu beberapa jam saja.
Kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Gotong royong dapat menjadikan pekerjaan yang berta menjadi ringan karena semula pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang akn terasa berat jika dikerjakan sendirian, tetapi jika dikerjakan secara bergotong royong akan menjadi ringan. Sebagai contoh seorang ibu rumah tangga akan terasa berat jika membersihkan rumah, memasak, bekerja, menyapu, sampai mengasuh anak sendiri, tetapi apabila seluruh anggota keluarga bisa bekerja sama pekerjaan tersebut akan terasa ringan dan menyenangkan, tidak menjadi beban. Ketika ibu memasak di dapur kakak menjaga adik, ketika ibu mencuci ayah membersihkan halaman, dan kakak membantu menyapu. Dengan demikian pekerjaan akan menjadi ringan.
Ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan. Gotong royong dapat memupuk persatuan dan kesatuan antar manusia. Bagaimanapun juga tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Mereka memerlukan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Adanya kerja sama yang baik antara manusia satu dengan manusia lainnya akan terjadi kerukunan hidup. Kerukunan hidup yang dipupuk secara terus menerus akan terjalin rasa persatuan dan kesatuan antar manusia.
Keempat, menghemat biaya. Biaya dapat ditekan apabila gotong royng digalakan di setiap kegiatan. Misalnya jalan kampung yang rusak, apabila masyarakat tidak mau bekerja bakti untuk memperbaikinya, secara otomatis akan mengundang pekerja atau tukang untuk memperbaiki jalan tersebut. Pekerja-pekerja tersebut harus dibayar menggunakan uang sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Apabila masyarakat mau bergotong royong memperbaiki jalan tersebut maka uang yang digunakan untuk membayar pekerja dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain.
Kelima, menumbuhkan rasa sosial. Gotong royong dapat menimbulkan rasa sosial yang tinggi antar sesama manusia. Misalnya saat terjadi musibah bencana alam di suatu daerah, orang-orang bergotong royong mengumpulkan dana untuk membantu mereka yang terkena bencana. Dengan memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain berarti kita telah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sumbangan yang dikumpulkan dapat mengurangi penderitaan mereka yang terkena musibah sehingga dapat mengurangi kesedihan mereka.
Keenam, menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri dapat tumbuh ketika kita melaksanakan kegiatan gotong royong. Kita bisa bekerja seperti orang lain, berarti kemampuan kita diakui oleh orang lain. Dengan demikian mantaplah dalam bekerja sama dengan orang lain.
Ketujuh, menumbuhkan semangat bekerja. Dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan dilakukan bersama dapat menimbulkan semangat untuk bekerja lebih giat. Teman yang banyak bisa menyelesaikan pekerjaan masing-masing, memacu seseorang untuk bekerja lebih baik, sehingga tidak ketinggalan dengan yang lain.
Kedelapan, tidak individualis. Manusia individualis adalah manusia yang hanya mementingkan kepentingan dirinya saja tanpa memperdulikan kepentingan orang lain di sekitarnya. Bergotong royong adalah bekerja sama yang ditujukan untuk kepentingan besama. Orang yang suka bergotong royong, berati lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri. Secara otomatis orang yang senang bergotong royong akan jauh dari sifat individualis.
Gotong royong tidak hanya dilaksanakan di masyarakat saja tapi juga dilaksanakan di rumah dan di sekolah. Contoh bergotong royong di sekolah antara lain membersihkan lingkungan sekolah, melaksanakan tugas piket di kelas, dan lain-lain. Sedangkan gotong royong di rumah contohnya adalah kegiatan membersihakan lingkungan rumah, mengerjakan tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain-lain.
Syarat Tumbuhnya Gotong Royong
Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: pertama, adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi; kedua, adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi; dan ketiga, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet,2003).
Lebih rinci Slamet (2003) menjelaskan tiga persyaratan yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi.
Pertama, kemauan. Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang: sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambatpembangunan; sikap terhadap penguasa atau pelaksanapembangunan pada umumnya; sikap untuk selalu inginmemperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri; sikapkebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dantercapainya tujuan pembangunan; dan sikap kemandirian ataupercaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutuhidupnya.
Kedua, kemampuan. Beberapa kemampuan yang dituntutuntuk dapat berpartisipasi dengan baik itu antara lain :kemampuan untuk mengidentifikasi masalah; kemampuanuntuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapatdilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi denganmemanfaatkan sumberdaya yang tersedia; dan kemampuanuntuk melaksanakan pembangunan sesuai denganpengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki.
Robbins (Soetomo, 2008) kemampuan adalah kapasitasindividu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.Lebih lanjut Robbins menyatakan pada hakikatnyakemampuan individu tersusun dari dua perangkat faktor yaitukemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
Ketiga, kesempatan. Berbagai kesempatan untukberpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh: kemauan politikdari penguasa/pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalampembangunan; kesempatan untuk memperoleh informasi; kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkansumberdaya; kesempatan untuk memperoleh danmenggunakan teknologi tepat guna; kesempatan untukberorganisasi, termasuk untuk memperoleh danmempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatanyang harus dilaksanakan; dan kesempatan untukmengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memeliharapartisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Sementara Mardikanto (Soetomo, 2003) menyatakanbahwa pembangunan yang partisipatoris tidak sekadardimaksudkan untuk mencapai perbaikan kesejahteraanmasyarakat (secara material), akan tetapi harus mampumenjadikan warga masyarakatnya menjadi lebih kreatif. Karena itu setiap hubungan atau interaksi antara orang luardengan masyarakat sasaran yang sifatnya asimetris (seperti: menggurui, hak yang tidak sama dalam berbicara, sertamekanisme yang menindas) tidak boleh terjadi. Dengandimikian, setiap pelaksanaan aksi tidak hanya dilakukandengan mengirimkan orang dari luar ke dalam masrakatsasaran, akan tetapi secara bertahap harus semakinmemanfaatkan orang-orang dalam untuk merumuskanperencanaan yang sebaik-baiknya dalam masyarakatnyasendiri.
Soetomo (2003) menjelaskan adanya kesempatan yang diberikan, sering merupakan faktor pendorong tumbuhnyakemauan, dan kemauan akan sangat menentukankemampuannya.
Dusseldorp (Kodoatie, 2003) membedakan adanyabeberapa jenjang kesukarelaan. Pertama, partisipasispontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasiintrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dankeyakinannya sendiri. Kedua, partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. Ketiga, partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya. Keempat, partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Dan kelima, partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.
Strategi Jitu Melestarikan Budaya Gotong Royong
Budaya gotong royong, perlu dilestarikan. Karenabudaya gotong royong bermanfaat, baik bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara, dan di antara manfaat dimaksud yakni: (1)meringankan beban, waktu dan biaya; (2) meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama; (3) menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan; dan (4) mempertinggi ketahanan bersama (Anonymous dalam Usman, 2024).
Untuk menegakkan tradisi gotong royong secara berkesinambungan, perlu untuk merubah sikap, mental dan menanamkan kembali nila-nilai gotong royong dalam masyarakat. Melaksanakan hal tersebut bisa dimulai dari: pertama, diri sendiri, yaitu meningkatkan kesadaran diri akan persatuan dan kesatuan, yakni dengan memahami serta mengimplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jika semua individu sadar akan fungsi dan peran mereka dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, serta dapat menyisihkan rasa egois dan menumbuhkembangkan kepedulian sosial, maka solidaritas akan tercipta dengan otomatis. Solidaritas tersebut dapat dipacu dengan menanamkan rasa senasib sepenanggungan, sikap saling menghormati, dan membiasakan diri untuk saling tolong-menolong. Maka perlu bagi generasi muda untuk tidak melupakan sejarah dengan meneladani sikap para pendahulu bangsa yang saling bergotong royong untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kedua, keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu agen penting untuk mewariskan nilai-nilai gotong royong sejak dini. Maka dalam keluarga harus dididik dan ditanamkan kepada anak akan nilai-nilai kebersamaan. Dengan musyawarah keluarga, anak membantu orang tua, sikap saling menghormati antar anggota keluarga, juga anak diajari akan arti tanggung jawab serta menumbuhkan kepedulian sosial. Anak juga perlu untuk diajari bagaimana berinteraksi kepada tetangga, mengingat bahwa orang pertama yang akan dapat dimintai bantuan disaat genting ialah tetangga terdekat. Selain itu sesama anggota keluarga wajib untuk mengingatkan anggotanya akan kewajibannya dalam kegiatan kerja bakti yang diadakan warga kampung disekitarnya.
Ketiga, organisasi pemuda (Karang Taruna dan Remaja Masjid). Pemuda sebagai salah satu unsur dari suatu masyarakat, dimana setiap aktivitasnya diharapkan mampu melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik. Maka organisasi pemuda Karang Taruna, Remaja Masjid, dan sejenisnya harus mampu berperan secara maksimal untuk membangun kemajuan desanya. Kegiatan kerja bakti dapat terwujud dengan baik apabila adanya kerjasama masyarakat dengan Karang Taruna dan Remaja Masjid. Karang Taruna dan Remaja Masjid menjadi penggerak serta contoh yang baik dengan mengulurkan tangannya kepada masyarakat, mengajak mereka bekerja bakti bersama. Para pemuda Karang Taruna dan Remaja Masjid bisa berinisiatif membuat agenda rutin kerja bakti yang harus dilaksanakan dengan kerja sama warga sekitar, juga kegiatan-kegiatan gotong royong seperti penggalangan dana, menjenguk warga yang sakit dan sebagainya.
Keempat, perangkat desa/pemerintah. Partisipasi perangkat desa/pemerintah sebagai pengendali sosial harus mampu mengajak warganya untuk mengikuti kerja bakti. Seminar dan sosialisasi kepada warga akan pentingnya kerja bakti perlu dilakukan. Atau yang lebih ekstrim lagi, mungkin dibuat suatu aturan atau sanksi bilamana warga melanggar dan tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan demi menertibkan warga agar tidak malas, membiasakan warga hidup disiplin dan untuk kebaikan bersama. Dengan cara yang agak represif seperti ini, lama kelamaan warga akan terbiasa hidup saling membantu, rukun, serta sadar tentang arti penting gotong royong dalam kehidupannya.
Dengan memulai dari hal kecil, seperti mengidupkan kembali tradisi kerja bakti, kita tidak hanya sekadar melestarikan budaya leluhur, namun juga dapat memperkuat karakter bangsa serta membawa banyak dampak positif bagi diri sendiri, orang lain, dan untuk Indonesia.
Gotong-royong dapat dikatakan sebagai ciri dari bangsa Indonesia terutama mereka yang tinggal di pedesaan yang berlaku secara turun-temurun, sehingga membentuk perilaku sosial yang nyata kemudian membentuk tata nilai kehidupan sosial. Adanya nilai tersebut menyebabkan gotong-royong selalu terbina dalam kehidupan komunitas sebagai suatu warisan budaya yang patut dilestarikan.
Merajut Kebersamaan
Gotong royong adalah kebersamaan. Menarik komentar Alfian (Usman, 2024) tentang kebersamaan. Terdapat lima pintu masuk untuk mengaktulisasikan Pancasila, dan kita bisa bebas lebih dulu masuk dari pintu mana. Tetapi dalam setiap pintu itu, terdapat satu prinsip yang kerap dilupakan, yakni kebersamaan. Dalam beribadah, bermuamalah, bersatu, bermusyawarah, kebersamaan diperlukan, guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama sebagai bangsa. Kebersamaan inilah yang kelihatannya telah terkikis. Ketika gotong-royong sudah jarang dijumpai dalam praktik nyata di lapangan, maka kehidupan kita sebagai bangsa menjadi terasa hambar. Kita merasa menjadi bangsa yang besar, tetapi minus aktualisasi gotong-royong, maka kebesaran itu hanya ada di atas kertas, dan sebagai bangsa, kita tidak bisa maju-maju.
Untuk menumbuhkan kembali kebersamaan itu, diperlukan pengorbanan dan pengendalian diri, yang bahasa agamanya mengendalikan hawa nafsu. Bahwa dalam setiap langkah kecil dari kehidupan kita, akan memiliki efek sosial yang besar. Kebersamaan dalam Pancasila mengajarkan kita untuk senantiasa mempertimbangkan efek sosial atas sikap dan pilihan kebijakan kita dalam kehidupan sehari-hari.
Revitalisasi Budaya Gotong Royong
Harus diakui kesakralan nilai budaya gotong rotong telah terkontaminasi dan terdegradasi cukup parah. Karenanya perlu revitalisasi. Revitalisasi budaya adalah upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, tradisi, bahasa, dan praktik budaya yang mungkin terancam punah atau terlupakan. Revitalisasi budaya juga bisa berarti memperbaiki dan memperbarui unsur-unsur budaya yang mulai luntur agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Revitalisasi budaya merupakan pelurusan kembali nilai-nilai budaya lokal yang mungkin banyak penyimpangan di kalangan penganut budaya, penyimpangan-penyimpangan tersebut bisa ditinjau dari perspektif agama, sosial, pendidikan, ekonomi maupun masyarakat, sehingga keberadaan budaya tersebut tidak merupakan salah satu pihak di satu sisi dan menguntungkan sisi yang lain (Mahmud, 2017).
Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan dan keberagaman warisan budaya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelestarian budaya.
Beberapa aspek penting terkait revitalisasi budaya : pertama, pelestarian. Yaitu menjaga keberadaan budaya dari kepunahan atau kehilangan nilai-nilai penting. Kedua, penghidupan kembali. Memberikan napas baru pada tradisi dan praktik budaya yang mulai ditinggalkan. Ketiga, adaptasi. Menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai budaya. Keempat, pemberdayaan. Melibatkan masyarakat dalam proses revitalisasi untuk memastikan keberlanjutan budaya. Kelima, peningkatan kualitas hidup. Mengaitkan revitalisasi budaya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial (AI, 2025).
Revitalisasi budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti : pertama, pendidikan dan sosialisasi.Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya budaya lokal melalui berbagai kegiatan. Kedua, pemanfaatan teknologi. Menggunakan media sosial, internet, dan teknologi lainnya untuk mempromosikan dan melestarikan budaya. Ketiga, pengembangan produk budaya. Menciptakan produk-produk kreatif berbasis budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi. Keempat, pengembangan pariwisata berbasis budaya. Memanfaatkan potensi budaya sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan. Kelima, penguatan lembaga adat. Mendukung peran lembaga adat dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal (AI, 2025).
Ada dua cara yang dapat dilakukan generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. Pertama, culture experience. Yaitu pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakan festival-festival. Dengan begitu, kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya. Kedua, culture knowledge. Yaitu pelestarian kebudayaan yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi atau untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah.
Selain itu, pelestarian budaya gotong royong dapat dilakukan melalui : pertama, riset dan kajian ilmiah; kedua, optimalisasi peran lembaga adat, lembaga kemasyarakatan, dan komunitas baik yang formal maupun nonformal; ketiga, inovasi budaya, namun tidak mencederai nilai luhur budaya gotong royong; keempat, pagelaran budaya; kelima, menjalin mitra sosial antar unsur yang meliputi akademisi (kaum pendidik), bisnismen, government, dan society (ABGs); keenam, internalisasi budaya lokal gotong royong pada kegiatan masyarakat; ketujuh, pemimpin “turun gunung”, artinya memberi contoh, mengajak, menghimbau, dan ikut dalam gotong royong. Bukan hanya sebatas praktisi seremoni; dan kedelapan, suluh budaya gotong royong secara terencana, kontinu dan intensif. Berkaitan dengan mempertahankan dan pelestarian budaya gotong royong, maka model pembinaan yang dapat dilakukan, meliputi: workshop, seminar dan diklat; integrasi pada mata pelajaran muatan lokal atau mata kuliah potensi lokal; bentuk organisasi kemasyarakatan gotong royong; pengamalan budaya gotong royong dalam setiap aktivitas (rapat, kerja bakti, musyawarah, dll); bangun teropong budaya; bangun gerakan struktur agresif (konektivitas desa/kelurahan sampai pusat); kolaborasi antar unsur yang ada dalam masyarakat; dan melakukan gerakan global budaya gotong royong.
Semoga bermanfaat !!!
*Dosen Universitas Mbojo Bima