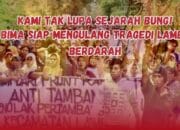Oleh : Ahmad Usman*
Kahaba.Net (13 Juni 2015) menurunkan berita dengan judul “Evaluasi Kota Layak Anak 2025, Wawali : Kota Layak Anak bukan Sekadar Predikat, Tapi Komitmen Bersama.” Wakil Walikota Bima Fery Sofyan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bima berkomitmen membangun kota yang ramah anak, sejalan dengan visi Kota Bima mewujudkan Kota Bima yang bermartabat dan berkelanjutan.
Menarik gubahan manis bernada puitis Sucher (1995). Anak seperti burung kenari di tambang batu bara. Mereka kecil, rentan dan butuh perlindungan. Akan tetapi sebagian besar dari jutaan anak yang hidup di kota belum merasa tenang dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, bermain, dan berekreasi, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh dan permukiman liar yang padat, dan perumahan yang kurang sehat serta kurang mendapatkan pelayanan umum seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah.
Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
Kota Layak Anak merupakan strategi pembangunan tingkat kota yang mengintegrasikan komitmet dan sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan NGO/LSM serta perguruan tinggi, dengan menggunakan perencaaan secara komprehensip dan menyeluruh berkelanjutan dalam bentuk program atau kegiatan yang digunakan untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak (Rustanto, 2011).
Kota Layak Anak merupakan program mengupayakan kebijakan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan upaya penyejahteraan bagi anak dalam beberapa aspek: pendidikan, kesehatan, sosial, hak sipil-partisipasi, perlindungan hukum, ketenagakerjaan, dan infrastruktur. Kebijakan tersebut pada awalnya diujicobakan di beberapa tempat, sebagai upaya awal untuk melakukan rintisan (Ramdhon, 2014).
Istilah Kota Layak Anak juga sering disebut Kota Ramah Anak. Menurut UNICEF Kota Ramah Anak adalah kota atau sistem pemerintahan lokal yang menjalankan pemenuhan hak anak. Ini merupakan kota di mana suara, kebutuhan, prioritas dan hak anak yang dimasukan ke dalam kebijakan publik, program maupun keputusan (www.unicef.org dalam Miskiyah dan Sri Yuliani, 2021).
Menjamin Hak-hak Anak
Kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak-hak anak sebagai warga kota. Berdasarkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hak anak sebagai warga kota (Suprayoga, 2007) adalah: keputusannya mempengaruhi kotanya; mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan; dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial; menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik;terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah;aman berjalan di jalan; bertemu dan bermain dengan temannya; mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hidup di lingkungan yang bebas polusi; berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, kecacatan.
Kota ramah anak adalah kota yang menjamin pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut, yaitu: identitas diri dan status kewarganegaraan; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; pendidikan; berpartisipasi sesuai dengan perkembangan mental dan tingkat kecerdasan; dan beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berkreasi, dan berekreasi.
Dalam pemenuhan terhadap identitas diri, sebuah kota yang ramah anak harus membuka akses yang seluas-luasnya bagi anak untuk mendapatkan kemudahan layanan administrasi. Pemerintah kota yang tanggap menjamin anak-anak yang dilahirkan di kota tersebut mendapatkan sertifikat kelahiran.
Pemenuhan terhadap kesehatan dan jaminan sosial diwujudkan sejak anak di dalam kandungan. Artinya, sang ibu yang sedang mengandung harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengakses layanan kesehatan. Seringkali ada kesulitan untuk keluarga yang berasal dari kelompok miskin perkotaan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Dengan demikian, perlu layanan kesehatan yang memudahkan keluarga dari kelompok miskin untuk memeriksakan kehamilan, mengobati anak mereka yang sakit, dan maupun penyuluhan terhadap pentingnya kesehatan.
Untuk kota metropolis, seringkali keluarga miskin sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas di sekitarnya karena segregasi sosial dan spasial. Layanan kesehatan yang berkualitas di pinggir kota dilayani di dalam kawasan permukiman baru yang dikelola oleh swasta. Sementara itu, layanan kesehatan yang berkualitas lainnya hanya dapat dijangkau di pusat kota yang memerlukan layanan transportasi kota untuk mendapatkannya. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan yang integratif yang mengkaitkan antara layanan kesehatan dengan transportasi yang terjangkau bagi warga perkotaan.
Sekolah-sekolah di perkotaan, meskipun dengan kondisi yang tidak sama kualitasnya, memberikan akses yang kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Memang ada perbedaan yang tajam antara sekolah swasta yang menarik bayaran tinggi dengan sekolah negeri di perkampungan miskin. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sekolah perlu dilakukan melalui program-program yang mementingkan pemerataan atas kualitas, seperti subsidi terhadap sekolah-sekolah negeri maupun swadaya yang terdapat di perkampungan.
Akses geografis terhadap sekolah pun perlu mendapatkan perhatian. Lokasi-lokasi sekolah ditempatkan berdekatan dengan lingkungan permukiman bagi penduduk yang dilayaninya dan layanan transportasi yang dengan mudah dapat diakses oleh anak-anak. Anak-anak dapat berjalan kaki di pedestrian yang terjaga kualitas fisik dengan desain yang “ramah” bagi fisiologis anak. Selain itu, lalu lintas di sepanjang permukiman menuju sekolah “disituasikan” sedemikian rupa sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak ketika bersekolah.
Adanya segregasi spasial antara “gated communities” dan perkampungan di sekitarnya tidak memungkinkan anak-anak bersekolah di lingkungan yang dibatasi tersebut, selain daya beli mereka terhadap sarana pendidikan kurang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa di antara anak-anak sendiri mengalami diskriminasi terhadap akses layanan pendidikan. Kota yang ramah anak jelas mengurangi kemungkinan adanya diskriminasi ini.
Arah Kota Ramah Anak
Suatu kota dapat dikatakan sebagai Kota Layak Anak apabila dari aspek fisik telah memenuhi beberapa kriteria yaitu sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, trotoar ramah anak, dan aspek nonfisik memenuhi unsur ramah, peduli pada anak, dan kasih sayang (Usman, 2014).
Sebuah kota/kabupaten masuk kategori layak anak jika daerah itu ramah terhadap anak. Arti ramah bermakna luas yaitu fasilitasnya yang ramah terhadap anak, seperti tersedia taman bermain, tersedia tempat pendidikan yang layak, serta lingkungannya yang ramah. Anak juga terpenuhi kasih sayangnya baik dari orangtua ataupun lingkungan sekitarnya termasuk sekolah.
Tujuan diadakannya program Kota Ramah Anak adalah untuk pemenuhan hak anak, mulai dari hak hidup, hak pertumbuhan, hak perlindungan, dan hak partisipasi.
Pada dasarnya tujuan dari suatu Kota Layak Anak bagi anak-anak muda menurut Riggio (2002) adalah: 1) mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kota tempat tinggalnya, 2) mengekspresikan pendapat, 3) berpartisipasi di dalam keluarga, komunitas dan kehidupan sosialnya, 4) memperoleh akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal, 5) memperoleh akses untuk meminum air yang sehat dan sanitasi yang memadai, 6) terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, 7) berjalan dengan aman di jalanan, 8) berjumpa teman dan bermain, 9) memiliki ruang hijau untuk tanaman dan hewan peliharaan, 10) tinggal di lingkungan yang sehat yang bebas polusi, 11) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, 12) didukung, dicintai dan memperoleh kasih sayang, 13) sama seperti warga lainnya dalam memperoleh akses terhadap setiap pelayanan tanpa memandang suku, agama, pendapatan, jenis kelamin dan keterbatasan (disability).
Arti Penting Penciptaan KLA
Arti penting dari penciptaan Kota Layak Anak adalah adanya ancaman obesitas (Tranter & Sharpe 2008 dalam Wilks 2010). Risiko lainnya yang kemungkinan muncul adalah kemunculan fenomena fatter, sicker and sadder seperti yang dikemukakan oleh Gleeson 2005 dalam Wilks 2010 dan kekhawatiran orangtua mengenai stranger danger (Valentine 1996 dalam Woolcock & Steele, 2008). Berangkat dari tiga hal tersebut, peranan dari penciptaan Kota Layak Anak sangatlah penting berdasarkan dari pengalaman Australia.
?Tujuan dari inisitif Kota Layak Anak adalah: (1) untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota; (2) untuk melaksanakan kebijakan kabupaten/kota yang layak anak; (3) untuk memobilisasi dan mengintegrasikan sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak; (4) untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; (5) untuk memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota, dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak; (6) untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintahan kabupaten/kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan (7) untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan (Patilima, 2004).
Menemukan Ruang bagi Anak Bermain
Anak memiliki hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berkreasi, dan berekspresi. Secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pemerintah berperan memberikan dukungan terhadap sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, dan tempat rekreasi.
Kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong penyediaan ruang bermain untuk permukiman baru seringkali tidak iikuti oleh developer properti. Seringkali pula disediakan ruang-ruang kosong, yang digunakan untuk lapangan bermain tanpa ditujukan secara khusus untuk bermain anak. Ketika digunakan untuk bermain, anak-anak harus bersaing dengan orang dewasa yang juga menggunakannya untuk berkumpul dan berolahraga. Selain itu, ruang-ruang kosong tersebut sebenarnya merupakan akal-akalan developer untuk mengelabui dinas teknis kota mengenai persyaratan ruang terbuka publik. Untuk beberapa lama kemudian, ruang-ruang kosong tersebut dijual oleh pengembang untuk pengembangan perumahan lebih lanjut. Tidak mengherankan, ditunjang dengan fasilitas bermain yang memadai di rumahnya, anak-anak di perumahan terencana seringkali beralih ke permainan indoor yang sedikit sekali menggunakan aktivitas fisik dan mengasah kemampuan bersosialisasi (AI, 2025).
Kondisi yang berbeda di permukiman kumuh, anak-anak bermain di berbagai ruang kosong yang tersedia, baik itu halaman rumah, pinggiran sungai, jalan, dan lain-lain. Tidak jarang, anak-anak tersebut bermain di jalan yang ramai dengan lalu lintas yang sangat membahayakan keselamatan.
Halaman sekolah dapat menjadi ruang bermain anak yang mudah diperoleh. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan mengenai kewajiban bagi satuan pendidikan (sekolah-sekolah) untuk memliki sarana, salah satunya, tempat olahraga. Melalui Permendiknas No. 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMU/MH mewajibkan sekolah-sekolah memiliki sarana bermain/olahraga yang memenuhi standar tertentu, di antaranya: 1. Tempat bermain / berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m2 / peserta didik; 2. Tempat bermain / berolahraga sebagian ditanami pohon penghijauan; 3. Tidak mengganggu proses pembelajaran; 4. Tidak digunakan sebagai tempat parkir; 5. Sarana yang disediakan distandarkan; dan 5. Ruang bebas yang memiliki permukaan yang datar, drainase yang baik dan tidak terdapat pohon, saluran air, dan benda-benda yang mengganggu.
Sayangnya, tidak seluruh sekolah mampu memenuhi standar tersebut. Hal ini sangat bergantung dari ketersediaan lahan dan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah kota untuk memenuhi standar tersebut. Rasionalisasi terhadap pemanfaatan ruang kota dalam bentuk efisiensi pemanfaatan lahan mendorong “mahalnya” lahan di perkotaan, sehingga penyediaan untuk sarana bermain ini tidak menjadi prioritas.
Kalau ada medianya, barangkali anak-anak kota sudah berteriak menuntut ruang bermain yang nyaman, aman, dekat dengan tempat tinggalnya dan bebas biaya. Sayangnya, anak menjadi prioritas ke sekian dalam penentuan tata ruang kota. Faktor ekonomi sampai saat ini masih menjadi push factor yang dominan, terlihat dari maraknya mega proyek pusat perbelanjaan, bangunan kantor, dan fasilitas yang memiliki ”nilai jual”. Jika dipahami lebih jauh, justru fasilitas ruang bermain memiliki nilai yang lebih tinggi karena membantu membentuk karakter manusia yang lebih menghargai pertemanan dan pertamanan (baca: lingkungan). Taman-taman kota yang menjanjikan ruang beraktivitas untuk penghuninya, merupakan lokasi potensial untuk ruang bermain anak (Anonymous, 2010 dengan judul “Ruang Bermain Anak”).
Sekali lagi, sayangnya, seringkali anak di kota dikategorikan sebagai user yang ke sekian sehingga kebutuhannya akan ruang bermain yang layak jarang dan bahkan tidak terpenuhi. Bermain merupakan aktivitas yang penting untuk anak-anak dalam pembentukan karakternya. Secara psikologis, aktivitas bermain melatih ketrampilan daya motorik kasar maupun halus dari anak, sehingga perkembangannya menjadi utuh. Karena itu, ruang bermain memiliki nilai yang tinggi dalam menampung wadah aktivitas bermain anak. Pada ruang bermain, anak bisa mengekspresikan dirinya, dan juga berteman dengan anak-anak lain. Social value pada anak ditumbuhkan dalam aktivitas bermain bersama yang diwadahi oleh fasilitas ruang bermain.
Berbentuk media edukatif untuk anak dalam berperilaku terhadap lingkungannya, alternatif ruang bermain di kota akan digambarkan masing-masing dengan keunikannya tersendiri yang memiliki tuntutan perilaku yang spesifik pula. Social valuemenjadi pesan yang penting pada buku yang akan disusun, karena pada ruang bermain, anak-anak berinteraksi sebagai mahluk sosial, baik dengan teman sebayanya maupun orang dewasa.
Ruang bermain pada ruang terbuka tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh anak saja, tapi juga untuk berbagai kalangan. Meski begitu, sebenarnya anak-anak tetap membutuhkan ruang bermain khusus yang sifatnya terbuka dan memang benar-benar ditujukan untuk mereka. Minimnya ruang bermain anak di perkotaan tercermin dari banyaknya anak-anak yang bermain di tempat-tempat yang bukan semestinya tempat bermain seperti di jalanan, bantaran kali, dan tempat yang kurang pas. Trend yang berkembang saat ini memang permainan anak-anak yang sifatnya di ruang terbuka akhirnya tidak populer dan mendorong anak-anak menjadi cenderung pasif dan individualis.
Situasi yang memprihatinkan ini memaksa anak-anak bermain di tempat bermain khusus dan tidak menggunakan tempat bermain di ruang terbuka yang merupakan sebuah ruang publik yang nyaman, karena memang tidak ada lagi ruang terbuka untuk bermain. Sering kita lihat banyak anak-anak bermain bola di jalanan beraspal, yang membahayakan nyawa mereka. Berkurangnya ruang terbuka publik ini tidak saja merupakan persoalan pakar lingkungan, tetapi menjadi beban psikologis masyarakat kota akan kebutuhan ruang sebagai aktualisasi diri (Sukawi, 2007). Maraknya pembangunan gedung (mall, ruko, kantor) semakin meminggirkan anak-anak yang sangat membutuhkan ruang terbuka hijau untuk tempat bermain. Kecenderungan anak-anak untuk memilih permainan modern yang tidak menuntut ruang spasial khusus bagi mereka tentu akan mempengaruhi psikologis perkembangan mereka nanti. Buruknya perkembangan ini pada anak tidak terlepas pada kemampuan pemerintah menyediakan ruang bermain khusus bagi anak tersebut.
Pentingnya Ruang Bermain bagi Anak
Pentingnya ruang bermain bagi anak-anak di kota, seperti diungkapkan Pearce (Sukawi, 2007), ruang bermain merupakan tempat dimana anak-anak tumbuh dan mengembangkan intelegensinya. Tempat dimana mereka membuat kontak dan proses dengan lingkungan, serta membantu sistem sensor dan proses otak secara keseluruhan. Dari tempat bermain pula, anak belajar sportivitas, disiplin dan mengembangkan kepribadiannya.
Pemerintah perlu mempelajari cara anak memenuhi hasratnya mendapatkan tempat bermain dengan mengikuti cara anak, dan bersedia bekerjasama dengan mereka untuk menata ruang yang ada. Menurut Hendricks (2002) perencanaan taman bermain yang ramah terhadap anak harus mempertimbangkan hasil konsultasi dengan anak, seperti bagaimana mereka menggunakan ruang dan apa yang mereka ingin lakukan, sehingga dalam proses pengembangannya tidak perlu melakukan pengekangan terhadap anak. Proses konsultasi dengan anak harus dilakukan dengan baik seperti yang dilakukan terhadap orang dewasa. Di beberapa negara seperti Inggris, Belgia dan Belanda, telah banyak contoh konsultasi yang dilakukan dengan anak mengenai tempat bermain.
Topik penting yang perlu diperhatikan oleh perencana dan perancang ketika melakukan diskusi dengan anak mengenai pembangunan taman bermain adalah masalah keselamatan anak.
Ada dua persoalan yang terkait dengan keselamatan anak : a. dibutuhkan tindakan pencegahan dan tenaga profesional yang berpengalaman untuk menjamin bahwa ruangan terbebas dari hal-hal berbahaya yang bisa menyebabkan anak-anak mendapatkan luka serius; b. orang dewasa, khususnya orang-tua anak dan pengawas tempat bermain diduga juga berpotensi untuk membahayakan keselamatan anak dan membuat anak takut. Persoalan ini menyangkut kasus kekerasan terhadap anak.
Selain itu, perencana dan perancang perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap anak. Menurut Sheri dan Bartlett (Patilima, 2012) dengan mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap tempat bermain anak, sehingga memungkinkan mereka merasa tenang dan nyaman. Pemerintah kota perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan di tempat bermain; meningkatkan keselamatan anak di tempat bermain; dan termasuk melakukan kampanye terhadap larangan penggunaan bahan berbahaya pada alat-alat permainan.
Partisipasi Anak
Partisipasi anak menjadi penting dalam kota yang ramah anak. Anak memperoleh kemungkinan-kemunkinan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebutuhan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi haknya.
Selama ini, perencanaan kota absen dari pelibatan anak dalam menentukan arah rencana kota. Dengan anggapan, suara anak telah diwakilkan oleh orang tua mereka. Selain itu, “perwakilan” anak di lembaga legislatif, selama ini secara formal tidak ada, karena anak tidak memiliki hak pilih. Dalam berbagai rentang kecerdasan anak, perencana kota dapat mendekati “anak” melalui berbagai teknik perencanaan yang disesuaikan. Dalam hal ini, anak dijadikan salah satu informan dan stakeholder bagi arah rencana kota.
Beberapa negara di Eropa mencoba menjajagi pendapat anak mengenai kota mereka melalui mengajak mereka menggambar atau mengekspresikan gagasan mereka terhadap visi kota.
Ada sejumlah hasil penelitian mengenai konsep Kota Layak Anak. Pertama, tergambar dari upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, hal ini terlihat dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak (Karsten & van Vliet, 2006); kedua, kemampuan akses anak terhadap lingkungan sekitarnya dalam hal pencapaian kota berkelanjutan dan kota ramah anak di Kota Christchurch, Selandia Baru (Tranter & Pawson, 2001); ketiga, penekanan arti penting bentuk kota (urban form) dan struktur sosial dan partisipasi anak di perkotaan di Kanada (Bridgman, 2004); keempat, peranan dan penggunaan ruang terbuka sebagai arena bermain anak-anak (Veitch, et al., 2007); kelima, berdasarkan pengalaman dari negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Swedia, Kanada dan Lebanon dikatakan bahwa program kota layak anak lebih fokus kepada kebebasan anak dalam bergerak dan berekreasi (Riggio, 2002).
Penelitian yang sangat berpengaruh pada implementasi Konvensi Hak Anak dan kemudian diadopsi oleh UNICEF dan UNHABITAT melalui “Child Friendly City Inniciative” adalah penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lynch, arsitek dari Massachusetts Institute of Technology. Penelitian dengan judul ”Persepsi anak terhadap ruang” dilaksanakan di 4 kota: Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara dan menggambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai: komuniti yang kuat secara fisik dan sosial, komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; adanya pemberian kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.
Dari sejumlah penelitian tersebut, yang sangat menarik bahwa anak, seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerjasama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan kota (Adams & Ingham, 1998). Pemerintah dapat berkonsultasi dengan mereka, karena mereka mempunyai persepsi, pandangan dan pengalaman mengenai lingkungan kota tempat mereka tinggal. Dari mereka, pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dan komitmen Negara lainnya di bidang anak.
Anak dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan. Anak akan memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka. Melalui kegiatan pelibatan ini anak menjadi berfikir mengenai persoalan lingkungannya, dan dapat mengidentifikasi persoalan yang ada untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Mereka juga dapat memberikan kontribusi dalam proses perencanaan dan pengembangan kota yang mereka harapkan (Adams & Ingham, 1998).
Indikator Kota Ramah Anak
Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para arsitek, perencana kota, perancang, psikolog, sosiolog, dan kriminolog yang berkaitan dengan anak dan kota, baik sebagai warga kota maupun pengguna ruang kota.
Pada penelitian tentang ”Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota” yang dilakukan oleh Hamid Patilima (2004) disimpulkan bahwa dengan membangun sarana kebutuhan masyarakat (orang dewasa), pemerintah kota menganggap bahwa kebutuhan anakpun telah terwakili dan terpenuhi dengan sendirinya. Padahal sesungguhnya, belum terpenuhi klebutuhan anak-anak.
Pemerintah kota masih mengabaikan terhadap anak bukan hanya pada kebijakan dan anggaran yang terbatas, tetapi juga pada pelayanan dan penyediaan sarana kota yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak.
Kota yang diinginkan oleh anak adalah kota yang menghormati hak-hak anak yang diwujudkan dengan (Innocenti Digest dalam Usman, 2024) : (1) menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan; (2) menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak; (3) menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkembang. Anak dapat berekreasi, belajar, berinteraksi sosial, berkembang psikososial dan ekspresi budayanya; (4) keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam; (5) memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua; dan (6) adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka.
Indikator Kota Layak Anak dibagi dalam dua kategori yaitu indikator umum dan indikator khusus. Indikator umum adalah dampak jangka menengah dan jangka panjang dari pengembangan kebijakan Kota Layak Anak dimana Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Badan Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota tidak terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut. Dalam hal ini peran KPP lebih pada pembuatan kebijakan agar tercipta suatu keadaan yang kondusif dalam rangka mempercepat pencapaian indikator tersebut. Sedangkan, indikator khusus adalah dampak jangka pendek dan jangka menengah dari pengembangan kebijakan Kota Layak Anak dimana Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menjadikan model Kota Layak Anak ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan menetapkan 7 (tujuh) aspek penting dalam pengembangan Kota Layak Anak yaitu: (1) kesehatan; (2) pendidikan; (3) sosial; (4) hak sipil dan partisipasi; (5) perlindungan hukum; (6) perlindungan ketenagakerjaan; dan (7) infrastruktur.
Indikator Kota Layak Anak seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berikut.
Pertama, untuk klaster hak sipil dan kebebasan meliputi : persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak; danjumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
Kedua, indikator Kota Ramah/Layak Anak untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi: persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
Ketiga, indikator Kota Ramah/Layak Anak untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi: angka kematian bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pojok ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan (i) tersedia kawasan tanpa rokok.
Keempat, indikator Kota Ramah/Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi: angka partisipasi pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
Kelima, indikator Kota Ramah/Layak Anak untuk klaster perlindungan khusus meliputi: persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
Langkah Menuju Kota Ramah Anak
Langkah-langkah menuju Kota Ramah/Layak Anak, dimulai dari: (1) penyusunan database anak, (2) pembentukan gugus tugas Kota Layak Anak, (3) revitalisasi forum anak, (4) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), (5) perlindungan anak, dan (6) sosialisasi Kota Layak Anak di tingkat sejumlah wilayah terkait (Ayu Yulia Yang dalam AI, 2025).
Di samping itu, juga dilakukan pembentukan gugus tugas kecamatan ramah anak, kampung/desa/kelurahan ramah anak dan sekolah ramah anak. Bukan hanya itu saja, melainkan juga studi banding Kota Layak Anak dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah inisiatif perlindungan anak hingga penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah Kota Layak Anak atau Peraturan Daerah inisiatif sebagai wujud komitmen politis DPRD dan Kota Ramah/Layak Anak.
Hak identitas adalah hak seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara. Hak perlindungan yaitu hak kepastian sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan pemberian jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah jaminan hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai yaitu jaminan anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai. Hak akses informasi yang layak adalah jaminan bagi penyedia informasi untuk mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yaitu jaminan setiap anak diperlakukan secara damai tanpa adanya kekerasan sedikit pun, termasuk ketika berhadapan dengan hukum.
Bimbingan dan tanggung jawab orang tua yang dimaksud adalah orang tua sebagai pengasuh utama anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak seperti penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.
Suatu kota/kabupaten menjadi Kota Layak Anak, apabila diterapkan dengan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam pembangunan. Menurutt Ery Syahrial (Usman, 2024), Pengarusutamaan Hak Anak adalah suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Kota Layak Anak akan sukses apabila: pertama, memiliki komitmen bersama yang dimulai dari pimpinan tertinggi pemerintahan di daerah hingga sampai ke stakeholder yang terkait anak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Biro PP dan PA), KPAID, LSM dan lembaga peduli anak lainnya. Kedua, penggunaan anggaran daerah yang rensponsif anak. Anggaran pembangunnan yang terkait dengan kepentingan anak harus ditingkatkan jumlahnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Contohnya 20 persen APBD untuk anggaran pendidikan bisa dikatakan anggaran yang responsif anak karena banyak anak yang menikmati manfaat dari anggaran tersebut. Ketiga, perencanaan pembangunan yang berperspektif anak. Segala bentuk rencana pembangunan yang dilakukan harus juga dilihat dari kacamata anak. Apakah proyek tersebut sudah ramah terhadap anak. Karena yang menikmati dan memakai hasil dari proyek pembangunan tersebut tidak saja orang dewasa, tapi juga anak-anak. Layak bagi anak sudah tentu layak bagi orangtua, sementara layak bagi orangtua belum tentu layak bagi anak. Keempat, mengeluarkan kebijakan–kebijakan daerah yang melindungi anak. Misalnya adanya keresahan masyarakat terhadap menjamurnya warnet yang telah mempengaruhi anak-anak dan memberikan dampak negatif karena tidak ada aturan selama ini. Maka pemerintah daerah merespon tuntutan masyarakat tersebut dengan mengeluarkan kebijakan soal aturan warnet bagi anak-anak. Kebijakan tersebut bisa dalam bentuk perda, SK walikota atau lainnya.
Konsep Kota Ramah Warga Itu Sederhana
Menurut Yayat Supriyatna (Nurjaman, 2013), seorang planolog Universitas Trisakti, sesungguhnya konsep kota ramah warga itu sederhana. Cukup mengacu pada empat prinsip tata ruang: aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Aman, artinya, kita bisa beraktivitas dan bebas dari ancaman bencana. Sedangkan nyaman mengacu pada kualitas kehidupan kota. Intinya, setiap orang harus bisa merasa senang dan menikmati keindahan kota sebagai ruang kehidupan. Di sinilah budaya urban menjadi denyut nadi kehidupan kota.
Dengan situasi aman dan nyaman, otomatis bakal memacu produktivitas warganya. Roda perekonomian kota akan terus melaju. Sektor riil akan bergerak. Sementara prinsip berkelanjutan mengandaikan segala potensi sumber daya dikelola dengan semangat “ada yang bisa diwariskan pada anak cucu kita. Maka, setiap praktik pembangunan kota dan aktivitas perekonomian warganya harus memperhitungkan, antara lain, daya dukung lingkungan, dan seterusnya.
Di sini, beberapa langkah maju yang sudah dilakukan beberapa pihak perlu diapresiasi. Contoh, pemasangan wi-fi di taman-taman kota, pembuatan lubang biopori di beberapa kota, atau swakelola sampah oleh warga di beberapa kampung kota, dan lain-lain. Memang belum bisa mengubah wajah kota secara dominan. Tapi sebagai pengalaman yang bakal menginspirasi tempat-tempat lain, upaya tersebut perlu ditampilkan juga.
Terakhir, tanpa mengabaikan kebijakan penguasa dan ahli perencanaan kota, partisipasi warga kota dalam mewujudkan kota yang nyaman juga perlu didorong. Sebab, partisipasi mutlak diperlukan dalam penataan kota. Kota adalah manusia yang menghuninya. Ide, pendapat, kehendak, kebutuhan, relasi sosial ekonomi dan politik warga adalah aspek-aspek yang membentuk dan menentukan warna, bentuk, dan sejahtera tidaknya sebuah kota.
Karena itu, semua aspek di atas sangat penting digali, didengar, dipenuhi dan diwujudkan. Ini akan memupuk rasa memiliki warga terhadap kotanya. Penataan dan pembagian ruang pun sesuai dengan kebutuhan warga kota. Keterlibatan warga akan mewujudkan kota yang demokratis dan terbuka.
Kota Layak Anak harapannya tidak sekadar menjadi lips service dan branding image dari stakeholder penyedia dan penyelenggara pelayanan publik. Kota Layak Anak dikukuhkan sebagai upaya pemenuhan hak anak-anak atas bentuk-bentuk pelayanan publik dan kerangka besarnya adalah pemenuhan dari Hak Asasi Manusia. Mencapai tujuan kesetaraan akses dalam pendidikan dengan mengambil tindakan menghapus diskriminasi berdasarkan gender, suku, bahasa, agama, usia, atau bentuk diskriminasi lain, pada seluruh jenjang pendidikan dan jika diperlukan membuat aturan untuk mengatasi hal tersebut.
Semoga bermanfaat !
*Dosen Universitas Mbojo Bima