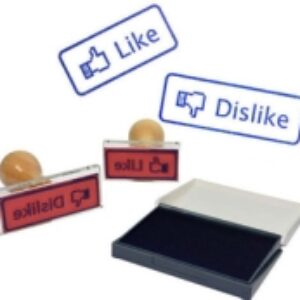Editorial, Kahaba.- Sederet kasus yang melanda bumi ‘Maja Labo Dahu’ sungguh telah menggusur entitas kedaerahan kita. Bakar-membakar nampaknya menjadi trend baru dalam menyelesaikan persoalan sosiologis kemasyarakatan. Tak hanya membakar gedung, bakar manusia pun menjadi tontonan yang mencengangkan di daerah ini.
Stekholder yang diharapkan menjadi panutan, kiranya tak ampuh lagi dalam menjadi suri tauladan di daerah ini. Pemuda kerap menjadi biang masalah yang meresahkan kehidupan bermasyarakat kita. Mengapa bima kian tergerus moral dan citranya? Jawabannya ada di tangan kita semua. Menciptakan Bima yang lebih baik, tentu peranan semua pihak sangat diharapkan.
Hukum yang menjadi panglima kehidupan masih saja tebang pilih dalam eksistensinya. Selera kekuasaan menentukan nasib kasus yang ingin dituntaskan. Elite politik sibuk mencitrakan diri, kalau pun jadi janjinya bagai kentut, berbau namun tak nampak.
Ke mana harus mengadu? Bumi ‘Maja Labo Dahu’ seolah ada namun arahnya tak menentu. Pejabat pemerintah sibuk menggilas satu sama lain demi perebutan kursi jabatannya. Pelajar dibebankan kurikulum sekolah yang belum tentu memberi jaminan di masa depannya. Pemuda sibuk rusuh dengan pemuda di kampung tetangga. Orang tua sakit kembali membayar mahar pengobatan medisnya. Rumah sakit, terisi oleh jiwa-jiwa yang sakit. Pengobatan penyakit fisik dan sosial di Bima seolah tak ada tempat yang pantas lagi.
Gerusan moralitas rakyat bima itu adalah ancaman. Jika pun di hukum, mungkin penjara tak mampu memenuhi penghuni masyarakat Bima yang berkasus. Nasib kesejahteraan di daerah ini seakan berada di jurang saja. Ingin sejahtera, harus membayar dan hal itu susah rasanya. Dewi hukum masih tertutup kain ‘merah’. Membukanya, butuh keberanian dan pengorbanan. Kepentingan selalu saja mengganjal setiap kehidupan yang harusnya berjalan secara normal. Bima kini menjadi daerah yang ‘aneh’. Tak ada penjajah, namun merdeka susah di rasa.
Sorotan media dan protes yang muncul kerap di pandang sebagai tindakan politik. Penyelesaiannya pun sarat nuansa politik. Tak mendukung kekuasaan, berarti tak mendapat posisi wenak (PW). Mendukung kekuasaan, tingkahnya semakin merajalela saja, selalu mencari pundi-pundi harta yang ingin dikurasnya. Bumi pertiwi mengadu pada generasi. Tapi, generasi tuli seakan kehilangan jati diri. Nurani menjadi dagelan sejati. Tak ada upeti, tak ada ‘barang’ yang jadi.
Ironi, Bima kini kehilangan pe-nghuni sejati. Membelanya harus kembali berhadapan dengan ‘tirani’. Ingin berekspresi, harus ikuti selera ‘permaisuri’. Kasus pungli menjadi kebiasaan untuk saat ini.
Itulah potret Bima yang kini tak lagi dapat kita banggakan.Dulu, kearifan lokalnya mampu mengundang negeri seberang belajar tata nilai di ‘bumi’ ini. Tapi itu cuman sejarah dan kebanggan lama. Bima kehilangan penduduk murninya. Setiap masalah, ‘tubuh Bima’ menjadi sasaran pelampiasan warganya. Tentu, ini bertentangan dengan nilai dan ajaran Bima di masa jayanya.
Bung Karno pernah berkata, ‘Jangan Lupakan Sejarah’, itu maknanya agar kita tetap kembali dan belajar dari nilai dan keluhuran sosial–yang dapat menyelamatkan daerah ini dari intervensi maupun gangguan pihak yang coba merusaknya. ***