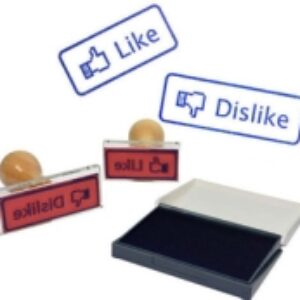Editorial, Kahaba.- Kekerasan selalu menjadi cara masyarakat dalam hidup berkomunal. Dulu, kekerasan/perang menjadi karakter tersendiri masyarakat Indonesia dalam upaya meraih kemerdekaan. Budaya itu seakan mendarah daging dalam diri pejuang kemerdekaan bangsa. Bagi negeri yang terjajah: perang, revolusi dan apapun metode kekerasan lainnya menjadi lumrah demi mempertahankan tanah kelahiran. Namun, menjadi langkah yang salah kaprah ketika kekerasan menjadi cara untuk mengisi kemerdekaan dan menghilangkan nyawa ‘saudaranya’.
1 Oktober kita mengenang lahirnya pancasila. Hari itu sepakat dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Kemerdekaan sudah 67 tahun lamanya. Namun, kekerasan selalu saja menggoda dan membangun konflik saudara yang seakan tak pernah berkesudahan. Kekerasan saat ini adalah cara ‘bar-bar’ dalam mengisi cita-cita kemerdekaan. Sejumlah konflik di daerah menjadi budaya laten dan cara baru bagi kita untuk hidup berbangsa dan berbhineka. Berawal dari konflik sepele; menyenggol saat joget di acara hiburan malam atau adu fisik di ajang kompetisi olahraga rakyat bisa menjadi sebab meledaknya konflik antar kampung. Sungguh menyedihkan keadaan masyarakat kita saat ini.
Mungkin bagi pelaku kekerasan, cara itu bagian dari menyelesaikan masalah. Di tingkat generasi/pelajar pun demikian adanya. Padahal, sejumlah anak masalah terlahir dari metode kekerasan. Dendam, proses hukum, instabilitas dan sejumlah keadaan penghambat pembangunan dan cita-cita bangsa terlahir dari konflik/kekerasan. Pendidikan pun menjadi sorotan dalam kasus kekerasan akhir-akhir ini.
Masyarakat Indonesia Timur khususnya di Bima kerap dikenal sebagai masyarakat yang ‘keras’ karakternya. Pendidikan pun belum mampu menjinakkan karakter masyarakat itu. Pola pikr humanis, sikap toleran dan saling menghargai seakan menjadi lembaran konsep di bangku pendidikan yang tak teraplikasi secara utuh. Pendidikan belum mampu menjadi jawaban dan mendobrak serta menyelesaikan paradigma kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan seakan terpelihara secara sistimatis tanpa ada yang mampu mengantisipasinya.
Perbedaan sesungguhnya menjadi hal yang lumrah dalam perspektif bangsa yang berbhineka. Kita mengakomodir itu dan sepakat membungkus dalam kemasan Pancasila. Namun, hadirnya kekerasan dalam tingkah laku dan cara hidup masyarakat, membuat Pancasila seakan tak sakti lagi. Pancasila tak lebih dari hiasan dinding di kantoran dan sekolah yang hilang nilai dan maknanya.
Kekerasan pun tak lahir dengan sendirinya. Kekerasan adalah ‘proyek’ bagi sebahagian kepentingan yang ingin bangsa ini rapuh. Bentuk penjajahan baru, akan mudah masuk di negeri ini ketika para penjaga benteng kemerdekaan (rakyat Indonesia) mudah di adu domba. Kekayaan alam terserap oleh kapitalis asing, di tengah para rakyat sibuk membangun konflik dan memperuncing perbedaan karena hal yang sepele seperti perbedaan agama, ras, kampung dan suku bangsa.
Pemerintah seakan menutup mata dari perannya. Mereka terlihat aktif biasanya setelah peritiwa kekerasan itu terjadi. Sederet pahlawan bertopeng seolah peduli selepas kejadian itu. Padahal, gelimangan darah, air mata bahkan nyawa telah tertumpah sia-sia di tanah yang katanya telah merdeka.
Kejadian di Bima akhir-akhir ini hampir tak pernah putus dengan berita kekerasan, konflik antar kampung (Roi-Roka, Bajo-Sarita, Samili-Godo, dan Renda-Ngali), demonstrasi anarkis, seakan menjadi bagian dinamika sosial yang dianggap wajar-wajar saja. Memang, Bima dulunya memiliki adat yang mempertontonkan kekerasan. Ada adat Ndempa (bertarung) di Ngali, Taji Tuta (adu kepala) di wawo, bahkan Gantao (adu fisik) di Raba.
Semua mempertunjukkan kesaktian dan kemampuan masyarakat dalam kemasan kekayaan adat budaya Bima. Esensi budaya itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Bima punya pengawal/rakyat yang tangguh dalam mempertahankan tanah kelahirannya dari ‘penjajah’. Budaya itu seakan tergeser nilainya. Cara-cara kekerasan (bar-bar, red) terkesan menjadi ajang kompetensi sungguhan bahkan nyawa dipertaruhkan dan menjadi tak ada harganya. Padahal mereka itu ‘bersaudara’ dan sengaja di peralat oleh sistem yang berkuasa. Masyarakat dibiarkan menganggur dan miskin agar gampang terprovokasi dan mereka (kapitalisme, red) mengambil untungnya.***